Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang seragam, apapun itu bentuknya. Fakta bahwa ada begitu banyak suku, budaya, agama dan norma hidup menunjukkan bahwa bangsa kita itu multi-etnis, multi-kultural, multi-agamis dan multi-pandangan. Seolah-olah sudah takdir bagi yang terlahir di Indonesia untuk menyadari kenyataan bahwa dirinya berbeda dari yang lain.
Namun fakta perbedaan itu tidak hanya ada pada lembaga-lembaga formal di atas saja. Sejarah dunia mencatat bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang begitu kompleks dan sangat plural. Bangsa Indonesia sudah mengalami segalanya—untuk menyebut satu per satu kondisi perbedaan yang lain: demokrasi dan kediktatoran militer, undang-undang dasar nonagamis dan syariah Islam, kekayaan ekstrem lapisan atas dan fight for survival orang kecil, nasionalisme dan separatisme, toleransi dan kekerasan ekstrem, Islam dengan mayoritas besar yang moderat dengan kelompok garis keras hingga yang ekstrem, korupsi yang meresapi semua bidang kehidupan masyarakat dan hukum yang bisa dipermainkan, tradisionalis dan modernis, lokalis dan globalis.
Pluralisme inilah yang seringkali menandai sikap kebanyakan orang Indonesia untuk permisif, seolah-olah “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Pindah situasi, pindah tempat, di situlah normanya berganti. “Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung.”
Mungkin sebagian besar orang akan beralasan bahwa dengan adanya pluralisme ini, sepantasnyalah kita menjunjung toleransi. Tetapi toleransi macam apa kalau jelas-jelas di depan mata terjadi tindak korupsi, namun dibiarkan begitu saja. Toleransi macam apa jika kemiskinan dan ketidakadilan rakyat kecil diabaikan, sedangkan sebagai wakil rakyat malah menuntut tunjangan 10 juta. Toleransi macam apa bila nyawa 202 orang di Bali dibiarkan sebagai bentuk penghargaan terhadap sebuah keyakinan tertentu. Bukankah itu sikap toleran yang permisif? Tidakkah ini berarti sikap toleransinya berdampak negatif? Masih adakah orang yang berani menjadi whistle blower ?
Memang benar zaman kita acapkali disebut era keruntuhan “narasi-narasi besar”. Pada era ini keyakinan yang bersandar pada nilai-nilai absolut mengalami gugatan serius. Di semua lini kehidupan, mulai dari sosial, politik, hukum, sampai seni seakan berlaku diktum: nilai apapun yang bertendensi menjadi absolut harus ditolak. Gugatan terhadap ‘absolutisme’ itu juga berlangsung pada ranah etika dan moral. Relativisme moral berpendapat ada banyak bentuk moralitas yang sama benarnya. Moralitas orang Barat, misalnya tak lebih benar daripada moralitas orang Asia. Ekstremnya, moralitasku berbeda dengan moralitasmu. Relativisme moral menyanggah klaim superioritas nilai moral. Dengan begitu, ia menawarkan jalan menuju pluralitas pilihan, pendapat dan opsi moral.
Oleh karena latar belakang di ataslah, tulisan singkat ini hendak mengupas problem serius atas terciptanya gugatan terhadap nilai-nilai absolut. Apa yang membuat seseorang atau kelompok tertentu berlaku permisif terhadap tindakan yang nyata-nyata melanggar prinsip dasar moral? Apa yang membuat seseorang atau kelompok tertentu seolah-olah menjadi seorang relativis praktis, tanpa harus mengatakan bahwa diri mereka adalah penganut relativisme? Lalu, hal-hal penting macam apa yang membuat seseorang seharusnya memegang dasar-dasar moralitas—sekaligus ini menggugat tindakan toleransi permisif?
Tulisan ini murni akan ditinjau dari sudut etika dan moral. Penulis sendiri akan banyak mengacu pada karya Mohammad Ali Shomali, seorang filsuf Iran kontemporer, yang berjudul Ethical Relativism (2001).
Kegagalan Menemukan Prinsip Moral yang Memadai
Menurut Shomali, sikap toleransi terhadap pluralisme pandangan yang condong bersifat permisif itu merupakan kegagalan seseorang untuk menemukan perangkat prinsip moral yang memadai. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berlaku demikian.
Pertama, sebagian orang tidak begitu cerdas atau terlalu malas untuk menempatkan prinsip atau nilai-nilai moral dalam sebuah hierarki nilai. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui atau memahami apa yang harus dilakukan ketika berbagai prinsip atau nilai saling bertentangan. Untuk hal ini, terutama penentuan hierarki nilai, kita berhutang banyak pada W.D. Ross, Max Scheler, dan von Hildebrand. Ross (1877-1971) memberikan jalan keluar terhadap etika Kant yang keras. Menurut Ross, setiap kewajiban selalu merupakan prima facie, artinya suatu kewajiban hanya bersifat mutlak sampai timbul kewajiban lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban pertama tadi. Dengan kata lain, suatu kewajiban adalah ‘kewajiban untuk sementara’. Apabila berdasarkan pertimbangan lain, ternyata kita tahu bahwa ada kewajiban lain yang lebih penting, kewajiban inilah yang harus didahulukan dari kewajiban pertama tadi. Dalam kasus di atas kiranya jelas bahwa tindakan menghargai nyawa sesama lebih penting daripada sebuah keyakinan ekstrem.
Sedangkan Scheler (1874-1924) mengatakan bahwa orang bertindak bukan demi kewajiban belaka, melainkan demi nilai-nilai. Analisis fenomenologis Scheler memperlihatkan bahwa nilai-nilai itu bisa digolongkan ke dalam empat bagian yang tersusun secara hirarkis. Pertama, nilai enak-tidak enak. Kedua, nilai vital, misalnya kesehatan dan keberanian. Ketiga, nilai rohani, yang meliputi nilai estetis (indah dan jelek) dan nilai etis (kebenaran dan keadilan). Keempat, nilai yang menyangkut obyek absolut (yang kudus, yang profan, dan nilai religius). Menurut Scheler, kewajiban moral terdiri dari keharusan yang dirasakan manusia untuk selalu merealisasikan nilai-nilai yang lebih tinggi di antara nilai-nilai yang mungkin terealisasikan. Namun ajaran Scheler ini diperbaiki oleh von Hildebrand (1889-1966) dengan membedakan antara nilai moral dan nilai non-moral. Kesehatan, misalnya, adalah nilai vital (nilai non-moral), namun kesehatan orang lain (nilai moral) adalah hal yang wajib saya perhatikan. Dengan demikian, jika seseorang benar-benar menggunakan akal budinya dalam menentukan tindakan moral, pastilah akan mempertimbangkan sistem hierarki nilai ini.
Kedua, orang berlaku permisif karena tidak mengetahui bahwa prinsip dan kaidah moral dapat diterapkan lewat berbagai cara, sesuai dengan beragamnya keadaan yang ada sepanjang berubahnya waktu dan masyarakat. Penerapan yang berbeda ini tidak berarti bahwa ada pluralitas prinsip dasar.
Ketiga, orang gagal menemukan prinsip moral yang memadai karena tidak menyadari banyaknya perbedaan yang sebenarnya merupakan akibat penerapan nilai-nilai dan prinsip umum yang berbeda dalam konteks keyakinan yang berbeda, misalnya perbedaan menyangkut sifat manusia, perbedaan alamiah antara jenis kelamin atau ras yang berbeda, dan menyangkut hubungan manusia dengan alam dan dunia adikodrati.
Keempat, terkadang orang berada dalam tekanan pikiran yang hebat sehingga terlalu berat untuk hidup dengan prinsip-prinsip moral. Di samping itu, terkadang ada banyak kepentingan praktis-psikologis yang dipilih seseorang untuk tidak menganut prinsip moral umum, misalnya mencari rasa aman.
Pertimbangan bagi Relativisme Moral Praktis
Mengenai bukti empiris bahwa tindakan yang dapat diterima secara moral cenderung berbeda-beda, baik antara berbagai masyarakat maupun antarwaktu, menurut Shomali, orang harus mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum menarik kesimpulan relativistik (yang menciptakan sikap toleransi permisif) dari bukti itu.
Pertama, meskipun tidak ada kesamaan dalam prinsip dasar mengenai sistem moral yang berbeda, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang fakta-fakta nonmoral atau meskipun mengira bahwa perbedaan-perbedaan itu muncul hanya karena orang telah menganut berbagai ukuran moral, orang tidak beralasan menyimpulkan bahwa semua ukuran alternatif yang dianut atau sebagian darinya mestilah benar.
Kedua, ada berbagai kesamaan moral yang penting di seluruh budaya. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa prinsip atau ukuran moral yang dapat diterima secara universal. Pojman (1998:47) mengetengahkan daftar prinsip umum yang mencakup larangan melukai dengan sengaja, membunuh orang yang tidak bersalah, menimbulkan penderitaan, menipu atau mencuri, dan prinsip yang menganjurkan kesetiaan terhadap janji atau sumpah, bersikap adil, berbicara jujur, tahu berterimakasih dan menolong orang lain. Sedangkan James Rachels (2004: 58-60) menyebutkan nilai inti yang sama bagi semua masyarakat dan sebenarnya diperlukan bagi eksistensi sebuah masyarakat, yakni keharusan merawat anak-anak (keturunan), keharusan berkata jujur, dan larangan membunuh. Dari kedua pandangan itu, ada kesimpulan teoretis yang bersifat umum, yakni adanya beberapa prinsip moral universal bagi semua masyarakat. Jika tidak demikian, tidak ada masyarakat yang bisa survive.
Ketiga, adanya perbedaan dan perselisihan moral sejalan dengan adanya prinsip-prinsip moral yang bersifat umum. Menurut Shomali, perselisihan moral itu lebih terletak pada “keragaman penerapan”. Dua budaya atau individu mungkin saja berpegang pada prinsip dasar yang sama namun cara menerapkannya berbeda, karena adanya keyakinan metafisis atau keadaan yang berbeda.
Keempat, ada beberapa implikasi yang tidak dapat ditoleransi dari penolakan terhadap ukuran dan prinsip-prinsip moral yang sah secara universal (implikasi yang tidak diinginkan oleh relativisme moral) : (1) tidak ada manfaatnya bersandar pada ukuran orang lain. Jika relativisme moral benar, kita dapat memutuskan apakah perbuatan itu benar atau salah hanya dengan bersandar pada standar masyarakat kita. Tetapi hanya sedikit orang yang berpikir bahwa masyarakat mereka mempunyai standar moral yang sempurna; (2) upaya pembaruan moral tidak masuk akal. Jika relativisme moral benar, pembaruan moral dan para pembaru moral tidak dapat dibenarkan, karena mereka bertentangan dengan ukuran-ukuran yang sudah ada. Misalnya, orang yang berjuang pada abad ke-8 untuk menghapuskan perbudakan adalah salah, karena mereka menentang perbudakan ketika perbudakan itu sendiri tengah populer; (3) konsep kemajuan dan moralitas ideal tidak bermakna. Biasanya kita berpikir bahwa setidaknya beberapa perubahan (kemajuan) dimaksudkan agar masyarakat kita menjadi lebih baik; (4) tidak ada manfaatnya kritik moral. Jika adat-istiadat berfungsi untuk menentukan apa yang baik dan adil, tentu tidak akan ada ruang untuk mengkritiknya. Jika relativisme benar, orang dapat membuat kritik internal menurut standar mereka sendiri; (5) tidak adanya keyakinan moral mengarah kepada nihilisme. Ini berkaitan dengan fakta bahwa relativisme terkadang diidentifikasi dengan bentuknya yang paling ekstrem yang berpendapat bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Namun ada juga fakta bahwa keyakinan dan komitmen moral bergantung pada cara memandang moralitas seseorang sebagai satu-satunya kebenaran atau yang paling masuk akal; (6) kegagalan mengevaluasi ukuran moral orang lain. Menurut relativisme moral, setiap ukuran moral suatu masyarakat tidak mungkin dinilai salah atau benar oleh orang lain. Oleh karena itu, agresi Nazi bukanlah hal yang tidak bermoral, karena menurut mereka sendiri tindakan mereka adalah benar. Kegagalan mencela perilaku semacam itu tampaknya tidak masuk akal. Agresi atau penjajahan selalu keliru di manapun ia berada.
Teori Relativisme Moral Modern
Pada bagian ini, saya sedikit menggambarkan usaha lain dari relativisme moral dalam membangun teorinya. Sekalipun tidak berkaitan langsung dengan relativisme moral praktis, setidaknya teori relativisme moral modern ini membantu kita untuk memetakan persoalan relativisme moral sebenarnya.
Gilbert Harman dan David Wong adalah tokoh relativisme moral yang penting dewasa ini, yang mencoba membangun argumen moderat guna menangkal serangan dan sanggahan terhadap relativisme moral. Mereka yakin bahwa argumen standar relativisme moral —bahwa dalam moralitas semua hal dibenarkan— tidaklah efektif atau bahkan tidak mungkin lagi untuk dianut. Mereka belajar banyak dari argumen-argumen lama, dan akibatnya memposisikan argumen mereka menjadi lebih rumit dibandingkan dengan argumen-argumen relativisme yang terdahulu.
Argumen pokok Gilbert Harman adalah pembahasannya mengenai dasar moralitas. Baginya, dasar moralitas tidak ada bedanya dengan sebuah konvensionalisme moral implisit. Moralitas bergantung pada tawar-menawar yang terjadi dengan sendirinya, yang menyesuaikan diri tanpa mesti dipaksakan diadakan perundingan tertulis. Konvensionalisme moral ini terjadi di dalam adat-istiadat atau budaya masyarakat, dan bisa saja berubah seiring dengan bingkai moralnya, yakni perubahan ruang dan waktu, pergantian generasi dan zaman.
David Wong membangun argumen relativismenya dengan mencoba mencari jalan tengah antara obyektivitas dan subyektivitas moral, mencoba mendamaikan pertentangan antara keduanya. Wong yakin bahwa moralitas merupakan kreasi sosial yang dirancang untuk mengatasi pertentangan batin dan antarpribadi (toleran). Kreasi sosial ini berbeda dengan teori konvensionalisme Harman. Teori relativisme moral Wong lebih bersifat kognitif, karena dia mampu menjelaskan dan mendefinisikan moralitas aktual yang sesuai dengan akal sehat dan pengalaman moral manusia. Bahkan dalam analisanya, dia menelurkan gagasan baru yakni mengenai “sistem moral yang memadai”. Dalam sistem inilah dia membedakan moralitas yang berintikan kebaikan dan moralitas yang berintikan hak.
Wong menjelaskan bahwa moralitas yang berintikan kebaikan menekankan cita-cita tentang bentuk tertentu kehidupan masyarakat di mana individu diterima dan berkembang, sedangkan moralitas yang berintikan hak menekankan hak-hak individu dalam kebebasan dan kebaikan yang lain, yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Kita dapat mengatakan bahwa moralitas yang berintikan kebaikan bekerja dengan konsep kebaikan umum menuju sebuah komunitas manusia. Moralitas tersebut menjelaskan berbagai bentuk sifat dan perbuatan sebagai kebaikan yang diperlukan guna mencapai kebaikan umum. Salah satu bagian penting dari moralitas semacam itu adalah pandangan tentang fungsi dan peran sosial. Sebaliknya, moralitas yang berintikan hak bekerja dengan beberapa konsep tentang kepentingan pribadi yang mendahului, atau terlepas dari partisipasi dalam sebuah komunitas. Moralitas semacam ini memberikan beberapa hak kepada individu untuk melindungi kepentingan mereka.
Dasar-dasar Moralitas
Membabi-buta meyakini relativisme moral sangatlah berbahaya karena berpotensi menjurus pada nihilisme dan anarki. Seperti yang sudah kita sadari pada awal tulisan ini, relativisme moral mengakibatkan seseorang begitu mudah menyatakan sikap toleransi alih-alih bersikap permisif saja. Orang dapat berbuat sesukanya atas nama toleransi, tanpa peduli tanggungjawab dan kewajibannya kepada sesama. Untuk itu, diperlukan seperangkat kriteria moral objektif yang bisa dijadikan pedoman bersama dalam menangani persoalan-persoalan moral pada umumnya. Pada bagian ini, secara menyeluruh akan dipaparkan gagasan Shomali mengenai dasar-dasar moralitas.
Moralitas dan Cinta-Diri
Menurut Shomali, moralitas didasarkan atas hasrat alamiah seseorang untuk memperbaiki diri sendiri dan keinginannya untuk mencapai cita-citanya. Teori ini dapat disebut ‘moralitas cinta-diri’. Untuk melindungi kepentingannya secara utuh, orang perlu memuaskan segala bentuk keinginan naluriahnya, termasuk keinginan untuk menjadi orang yang baik. Orang yang mencintai diri sendiri dan mencintai orangtua, anak-anak, kerabat dan sahabatnya mungkin pula mencintai semua manusia, hewan dan alam. Manusia tidak akan merasakan kehidupan yang menyenangkan jika mereka menyaksikan orang lain menderita atau kelaparan. Kepedulian mereka pada diri sendiri, demi kebahagiaan dan kesempurnaan mereka, mengharuskan mereka bersikap baik. Dengan demikian, teori moralitas cinta-diri mengakomodasi keinginan intrinsik dan asasi dalam diri manusia untuk membahagiakan orang lain, meskipun tidak ada kaitannya dengan kepentingan langsung manusia tersebut. Jadi, semua perbuatan yang disengaja dari setiap pelaku tindakan berasal dari keinginan asasi atau kecenderungan untuk memuaskan perhatian dan kepentingannya.
Di sini memang perlu dicatat bahwa cinta-diri sangat berbeda dengan mementingkan diri sendiri. Perbedaan antara egois dan tidak egois bukanlah ada atau tidak adanya cinta-diri. Perbedaan itu terkait dengan cara seseorang mempertimbangkan kepentingan dan tujuan serta mencoba memenuhi syarat-syarat cinta-diri.
Shomali menyimpulkan bahwa hasrat asasi dan kepentingan manusia yang membentuk moralitas bergantung pada watak manusia, yang memang sama pada setiap manusia. Ada hubungan nyata antara watak manusia dan hasrat maupun kepentingan di dalamnya, dan kedudukan moral dari setiap perbuatan bersumber dari hubungan nyata semacam itu. Dengan kesimpulan ini, pemikiran Shomali tentang moralitas berbeda dengan teori Harman yang yakin bahwa tuntutan moral hanya berlaku pada orang-orang yang memang ingin mengikutinya.
Membuat Keputusan Moral
Moralitas cinta-diri menentukan setiap manusia dalam mengambil keputusan moral. Lewat keputusan moral inilah, manusia mampu menentukan prinsip dasar moral universal, dan tidak membiarkan sikap permisif menguasai dirinya. Untuk sampai pada pengambilan keputusan moral, manusia akan melewati beberapa tahap rumit yang dipengaruhi beberapa faktor. Shomali mencoba menjelaskannya dengan memulai dari faktor pertama, yakni pemahaman dan penilaian. Menurutnya, manusia akan mustahil membuat keputusan tanpa memahami masalah tersebut. Manusia mesti berpikir tentang perbuatan itu dan akibatnya, manfaatnya ataupun kekurangannya. Baru setelah kita mempertimbangkannya, kita akan membuat penilaian terhadap perbuatan itu, benar atau salah. Lalu memutuskan untuk melakukannya atau tidak sama sekali. Selain itu, faktor ini juga mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan di mana keputusan itu berangkat dari tindakan yang sudah pernah kita lakukan. Di sini, pemahaman dan penilaian menjadi semacam evaluasi diri.
Faktor kedua adalah melihat motivasi apa di belakang keputusan itu. Di sini Shomali mencoba membedakan antara ‘penalaran teoretis’ dan ‘penalaran praktis’. Penalaran teoretis berkaitan dengan keyakinan dan penalaran praktis berkaitan dengan hasrat atau niat. Shomali berpendapat bahwa setiap penalaran praktis didahului oleh beberapa bentuk penalaran teoretis. Pada mulanya seorang pelaku menemukan beberapa alasan untuk meyakini bahwa dalam kenyataannya perbuatan tertentu adalah kondusif atau tidak kondusif bagi cita-citanya. Kemudian, setelah menemukan beberapa alasan untuk meyakini bahwa salah satu alternatif memang lebih baik, dia mendapatkan sebuah motivasi untuk berbuat sesuai dengan alternatif itu. Hanya setelah termotivasi kita berniat atau memutuskan untuk melakukan perbuatan tertentu. Di sini dan selama melakukan penilaian, peran emosi dan hasrat sangatlah penting. Selain kedua peran itu, Shomali menambahkan bahwa peran akal tidak kalah pentingnya dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, tiga peran yang disebutkan Shomali menjembatani sekaligus antara emotivisme, hedonisme dan etika Kantian.
Shomali sependapat dengan Hume bahwa manusia punya kecenderungan bawaan untuk bersimpati terhadap orang lain. Atau seperti yang telah Shomali katakan bahwa setiap orang telah dibekali oleh moralitas cinta-diri.
Usaha demi kesenangan atau untuk memuaskan hasrat, tidak berarti kita menerima bentuk hedonisme murni. Shomali menyebutkan ada berbagai bentuk hasrat dan dengan demikian ada pula berbagai bentuk kesenangan. Dia setidaknya menyebutkan tiga bentuk. Pertama, hasrat ‘fisik’ atau ‘sensual’, yakni hasrat yang menimbulkan kesenangan fisik atau sensual, misalnya kesenangan yang muncul karena merasakan makanan yang lezat. Kedua, hasrat ‘semi-abstrak’, yakni hasrat yang tidak secara langsung disebabkan oleh hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak berhubungan langsung dengan indera kita, misalnya kesenangan yang dirasakan orang karena mempunyai uang atau jabatan yang tinggi. Ketiga, hasrat ‘abstrak’, inilah hasrat sejati yakni hasrat yang dapat kita rasakan secara langsung, independen dan tidak dapat direduksi kepada hasrat yang lain, misalnya kesenangan yang diperoleh seseorang ketika dia memiliki rasa percaya diri atau rasa tenteram dalam pikiran atau perasaan bahagia. Hasrat abstraklah yang dimaksud Shomali dalam kaitannya dengan moralitas kita. Menurutnya, hasrat abstrak bukan hanya tidak mengarahkan kita kepada perbuatan jahat, tetapi bahkan cenderung menimbulkan sifat yang positif dan baik.
Dengan penjelasan tentang pengambilan keputusan di atas, Shomali berhasil menunjukkan bahwa moralitas baik dan buruk sama sekali tidak bersifat konvensional, tetapi benar-benar ada dan dapat diwujudkan atau ditemukan oleh akal budi manusia dengan cara memperhatikan sifat, bakat, dan potensialitas manusia. Dan itu ukurannya sama pada setiap manusia. Oleh karena itu sifatnya universal.
Peran-Peran dalam Pengambilan Keputusan
Selanjutnya, Shomali mengatakan bahwa ada peran internal dan eksternal dalam keputusan moral manusia. Shomali yakin bahwa adanya pemahaman yang benar terhadap peran ini dapat menjelaskan situasi yang kondusif bagi seseorang dalam menentukan sikap moral. Shomali menyebutkan lima macam peran. Pertama, peran keyakinan, pengetahuan dan informasi.
Salah satu bagian penting keputusan moral kita adalah cara kita memahami sebuah persoalan, kemudian cara kita mendapatkan hasil dan akibat-akibat dari setiap sisi persoalan. Perbedaan dalam tataran ini dapat menghasilkan keputusan yang berbeda walaupun masalahnya sama. Bahkan orang yang memiliki cita-cita moral yang sama tidak terlepas juga dari perbedaan ini.
Kedua, peran hasrat. Hasrat merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan kita. Seperti sudah dijelaskan di atas, meskipun hasrat sejati sama pada semua manusia, mungkin penerapannya berbeda. Yang perlu ditekankan pada hasrat sejati adalah arahnya yang selalu pada perbuatan baik. Sedangkan hasrat fisik, sifatnya netral, maksudnya dapat dipuaskan dengan cara yang bermoral maupun tidak bermoral. Dari sinilah seringkali perbuatan buruk berasal.
Ketiga, peran keinginan dan keputusan seseorang. Meskipun ada banyak pembatasan yang diakibatkan oleh berbagai keadaan internal dan eksternal, manusia bebas untuk membuat keputusannya. Tanpa keyakinan akan kehendak bebas, maka sebenarnya tidak ada moralitas. Dan dalam kehendak bebasnya itu, manusia pastilah menganut nilai atau cita-cita yang mengarahkan perbuatan mereka.
Keempat, peran kemampuan mental dan intelektual serta bakat (misalnya kebiasaan baik). Kelima, peran keadaan. Yang dimaksud dengan keadaan adalah sifat atau ciri khas yang berada di sekitar pembuatan keputusan. Itu bisa keadaan fisik dan mental pelaku (mis: sehat atau sakit), perasaan pelaku (mis: senang atau sedih), kemampuan pelaku, keadaan orang lain yang terlibat, waktu, tempat, hukum, budaya, sumber alam yang ada, alat, dan sarana. Setiap perubahan dalam kondisi ini akan mengharuskan pelaku mengubah penilaian terhadap keputusan atau tindakan mereka.
Selanjutnya Shomali menjelaskan bahwa setiap keputusan mestilah memenuhi syarat-syarat pilihan rasional. Dalam hal ini, Shomali mengadopsi pemikiran Paul Taylor. Taylor percaya bahwa sebuah pilihan adalah rasional selama ia bebas, tercerahkan, dan netral. Tetapi situasi ini memang sedikit utopis, karena Taylor sendiri yakin bahwa tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas, tercerahkan dan netral. Namun Shomali menganjurkan hal ini sebagai alat bantu bagi pelaku tindakan untuk membuat penilaian dan keputusan yang lebih baik.
Syarat-syarat kebebasan adalah tidak ditentukan oleh motif yang tidak disadari, tidak dalam keadaan terpaksa atau dengan kata lain orang tersebut sepenuhnya sadar akan dirinya sendiri, tidak ditentukan oleh hambatan eksternal, dan segala pilihan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan orang itu sendiri. Syarat pencerahan adalah mengetahui hakikat jalan hidup yang dipilih, mengetahui segala kemungkinan akibat-akibat dari menjalani suatu pandangan hidup, dan mengetahui sarana apa yang diperlukan untuk menjalankan pandangan hidup itu. Syarat sikap netral adalah bersifat murni, tidak memihak atau bersifat objektif, dan tidak menyimpang, maksudnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis bawaan yang kronis.
Sifat Manusia: Hal yang Diabaikan oleh Relativisme Moral
Setelah mengikuti alur penjelasan Shomali di atas, terakhir dia menekankan bahwa adanya perbedaan cita-cita atau nilai moral semata tidak menyiratkan bahwa tidak ada satu moralitas yang benar dan paling masuk akal. Menurutnya ada hubungan nyata antara cinta-diri kita dan hasrat, cita-cita dan sifat kita yang sejati. Agar mampu menunjukkan adanya cita-cita yang sejajar itu, kaum relativis harus menunjukkan adanya perbedaan jenis sifat manusia. Masyarakat atau individu dengan sistem moral yang berbeda harus terbukti tidak termasuk dalam spesies manusia yang sama. Dan itu tidak mungkin! Salah satu implikasi yang tidak dikehendaki dari pandangan ini adalah bahwa jika seseorang atau sebuah masyarakat memutuskan untuk menganut sebuah moralitas baru, maka orang itu atau masyarakat itu pertama-tama harus mengubah sifat-nya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat mengubah pendirian moral mereka, kecuali jika sifat mereka sudah diubah. Inilah, menurut Shomali, yang tidak dapat diterima oleh kaum relativis.
Kajian tentang sifat manusia jauh lebih sulit daripada yang dapat dilakukan dalam pembahasan tentang relativisme moral. Menurut Shomali ada alasan yang baik untuk berpikir bahwa manusia memiliki sifat yang sama. Tentu secara biologis manusia itu sama. Tetapi yang dimaksud Shomali dengan sifat manusia lebih dari sekadar unsur biologis. Sifat manusia merupakan pandangan ontologis yang menciptakan sifat-sifat yang sama pada semua manusia. Seandainya tidak ada sifat semacam ini di antara manusia, tentu tidak akan ada ruang bagi disiplin ilmu-ilmu. Semua ilmu ini berasumsi bahwa manusia itu sama dan bersikap sama dalam keadaan yang sama.
Manusia terikat dengan sifat mereka dan manusia dengan sifat yang sama itu tidak dapat menganut moralitas yang berbeda. Kaum relativis harus menunjukkan bahwa manusia yang berada dalam keadaan yang sama dapat memiliki moralitas yang berbeda. Ini bisa dianalogikan seperti misalnya kesehatan. Manusia dalam keadaan yang berbeda mungkin membutuhkan bentuk perawatan yang berbeda atau jenis makanan maupun vitamin yang berbeda. Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa manusia secara biologis dan fisik hampir sama dan dalam keadaan yang sama mereka membutuhkan gizi dan perawatan kesehatan yang sama. Oleh karena itu, perbedaan dalam bentuknya tidak berarti bahwa kesehatan bukanlah tujuan, atau tidak ada prinsip umum menyangkut kesehatan.
Dengan demikian, objektivitas moral atau penolakan terhadap relativisme moral tidak memutlakkan bahwa semua orang harus berbuat sama. Orang yang berbeda dengan sifat yang sama secara moral bisa diharapkan untuk berbuat secara berbeda. Yang diduga akan dilakukan oleh seorang anak kecil berbeda dari apa yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Hal yang benar bagi seorang wanita dalam kedudukannya sebagai seorang ibu jelas berbeda dari hal yang benar bagi seorang wanita dalam kedudukannya sebagai seorang anak, saudara, atau istri. Orang yang sama, dengan peran yang sama secara moral, bahkan mungkin saja harus melakukan sesuatu yang bertentangan pada waktu atau tempat yang berbeda. Misalnya, Ibu M yang harus menyusui anaknya yang masih bayi, tetapi dia tidak boleh berbuat serupa ketika anak-anaknya itu sudah dewasa. Oleh karena itu, berasumsi bahwa orang yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda atau kewajiban maupun tanggungjawab yang berbeda tidak membuktikan relativisme.
Karakteristik Cita-cita Moral yang Benar
Dengan menggunakan pemikiran yang telah dikembangkan sebelumnya, Shomali mencoba menyusun argumennya tentang absolutisme. Argumennya berangkat dari kenyataan bahwa setiap manusia pasti memiliki cita-cita. Dalam prakteknya, manusia menganut berbagai bentuk cita-cita. Cita-cita ini dibentuk oleh berbagai faktor, semisal agama, budaya, pendidikan, profesi, dan lingkungan keluarga. Cita-cita yang dianut melalui cara ini mungkin saja berbeda dan memang bertentangan satu sama lain. Tetapi memiliki fungsi yang sama, yakni menentukan nilai seseorang dan menciptakan bentuk kehidupannya. Setiap orang yang berakal harus selalu memikirkan cita-citanya dan melihat apakah cita-cita itu layak dianut sebagai cita-cita atau tidak. Maka di sini, kita harus membedakan antara apa yang Shomali sebut sebagai cita-cita moral yang sejati dan apa yang secara kebetulan (relatif) dianut sebagai sebuah cita-cita moral.
Shomali menyusun enam karakteristik cita-cita moral yang sejati. Pertama, cita-cita moral yang sejati pastilah selaras dengan sifat manusia. Kedua, cita-cita moral yang sejati pastilah dapat dipahami oleh akal kita, sehingga kita bisa mengikutinya. Ketiga, cita-cita moral itu memenuhi syarat rasional, yakni bebas, tercerahkan dan netral. Keempat, cita-cita moral yang sejati pastilah didukung oleh hasrat sejati kita. Jika tidak demikian, ia tidak dapat menggerakkan kita untuk bertindak menurut apa yang kita anggap baik bagi kita. Kelima, cita-cita moral yang sejati pastilah dapat dicapai dan bersifat praktis. Jika tidak demikian, ia hanyalah mimpi saja dan bukan pedoman hidup. Keenam, cita-cita moral yang sejati mampu mencakup nilai dan ukuran moral yang lain dan menempatkannya dengan tepat dalam tingkatan nilainya, sehingga dapat menjelaskan tujuan atau nilai yang dituju atas suatu perbuatan.
Menurut Shomali, cita-cita memiliki kedudukan penting dan krusial dalam sistem nilai manusia. Terlepas apa atau bagaimana seharusnya cita-cita moral itu, dan terlepas apakah “baik” dapat didefinisikan atau tidak, bagi setiap orang, cita-cita moral merupakan kebaikan tertinggi. Jika misalnya kita menanyakan setiap orang tentang alasan tindakannya, lambat laun dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak dapat bertolak lebih jauh lagi. Titik inilah yang kita anggap sebagai cita-citanya atau tujuan tertingginya. Sedangkan tujuan-tujuan lain hanyalah suatu rangkaian tujuan yang muaranya adalah cita-cita tertinggi itu. Kedekatan atau kejauhan tujuan-tujuan lain tadi dengan tujuan tertinggi akan menentukan kedudukan setiap tujuan atau nilai dalam sistem moral tersebut. Dengan mempertimbangkan hierarki nilai itu, pelaku tindakan dapat memutuskan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik praktis antara beberapa nilai. Orang harus membedakan antara yang baik dan yang lebih baik atau antara yang buruk dan yang lebih buruk. Shomali menambahkan bahwa argumen relativisme moral sebenarnya berangkat dari perselisihan membedakan manakah hierarki nilai yang benar.
Tali Simpul: Menyoal Korupsi
Pada bagian terakhir Shomali mengembangkan teori tentang dasar-dasar moralitas. Dia mencoba menyelami hakikat moralitas, cita-cita moral dan sifat-sifatnya, berbagai faktor yang terdapat dalam proses itu dan hasil dari pengambilan keputusan. Menurut Shomali, setiap sistem moral didasarkan atas cita-cita moral. Pada mulanya cita-cita moral menentukan nilai seseorang dan kemudian menata nilai-nilai itu. Bagi setiap orang, cita-cita moralnya merupakan kebaikan tertinggi atau tujuan akhir. Cita-cita moral kita pada gilirannya ditentukan oleh cinta kita kepada diri sendiri, dan dapat disimpulkan sebagai keinginan untuk hidup bahagia. Status moral setiap perbuatan bergantung pada hubungan antara perbuatan itu dan cita-citanya. Sebuah perbuatan adalah baik jika ia dapat mengantar kita pada cita-cita kita. Cinta kita kepada diri sendiri juga membentuk serangkaian hasrat yang mungkin memberi kita motivasi yang memadai untuk melaksanakan apa yang diajarkan penalaran praktis kepada kita. Hal itu menjadi sarana yang baik demi mencapai cita-cita, tujuan dan maksud kita. Apapun yang dituntut oleh hasrat sejati kita (hasrat yang nyata dan tidak dapat direduksi) menjadi nilai alamiah bagi kita. Fakta ini sangat erat kaitannya dengan fakta lain, bahwa “baik” dan “buruk” tidak bersifat konvensional, tetapi benar-benar ada dan dapat diwujudkan serta ditemukan oleh akal manusia dengan cara mencermati hakikat, bakat, potensi, dan kesempurnaan manusia.
Selanjutnya Shomali mengatakan bahwa satu-satunya usaha yang masuk akal bagi kaum relativis atau penganut toleransi permisif adalah menunjukkan bagaimana setiap individu atau masyarakat dapat menganut cita-cita yang sejajar dan rasional. Namun, agar mampu menunjukkan adanya cita-cita yang sejajar itu, mereka harus membuktikan adanya bermacam-macam sifat manusia, sebab menurut Shomali ada hubungan yang nyata antara cita-cita dan sifat manusia. Masyarakat atau individu, dengan bermacam sistem moral harus dianggap bagian dari spesies manusia yang berbeda, bukan bagian dari apa yang biasanya kita pahami sebagai sifat manusia yang sama. Dengan menyebutkan implikasi yang tidak masuk akal dari asumsi ini, Shomali berpendapat bahwa sikap menerima perbedaan sifat manusia tidak malah berarti mendukung toleransi permisif. Sebab manusia terikat pada sifatnya. Orang yang sama tidak dapat menganut moralitas yang berbeda, sedangkan kaum toleran permisif harus membuktikan bahwa orang yang sama dalam keadaan yang sama benar-benar dapat memiliki moralitas yang berbeda.
Dengan demikian, apa yang digagas oleh Shomali mengenai dasar-dasar moralitas memberikan jawaban yang memadai mengenai aspek penting yang dapat mengubah seseorang melakukan tindakan moral universal. Wacana-wacana kontemporer seperti multikulturalisme, HAM, korupsi, aborsi ataupun etika lingkungan di Indonesia dapat berpijak dari teori ini.
Baiklah bila di akhir tulisan ini, kita memakai gagasan Shomali sebagai pisau cukur dalam menjawab persoalan tentang korupsi. Setidaknya ada tiga permasalahan di balik korupsi. Pertama, budaya korupsi mewabah karena adanya prinsip tahu sama tahu di antara orang-orang di dalam birokrasi apapun di negeri kita ini. Ada semacam konvensionalisme moral implisit, toh sama-sama melakukan korupsi, jadi tidak perlu dilaporkan apalagi dibicarakan —sambil diam-diam memasukkan uang ke dalam kantongnya. Makanya, para koruptor tidak merasa bersalah dengan tindakannya karena mereka memiliki alibi bahwa ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dengan demikian kalau ada banyak orang melakukannya, kejahatan tersebut adalah sesuatu hal yang biasa. Akibatnya, kebiasaan itu menciptakan hak. Dan kalau satu dituntut, lalu semua harus bertanggungjawab. Kalau “semua bertanggungjawab” bukankah sama saja dengan tak ada yang bertanggungjawab? Ini berarti di antara mereka sendiri tidak mungkin saling menyalahkan. Di sini timbullah semacam kreasi sosial, yang secara tidak sengaja dirancang untuk mengatasi pertentangan antarpribadi. Lebih baik membiarkan saja –toleran dan bertindak permisif— daripada ikut terjerat dalam hukum.
Kedua, tiadanya sanksi hukum membuat orang berani melakukan korupsi karena yakin tidak ketahuan atau didiamkan saja. Ketiga, korupsi itu berwajah banyak atau anonim, sebab yang dirugikan tidak langsung tampak sebagai pribadi, terutama yang terkait dengan penyelewengan uang negara atau rakyat. Siapa yang dirugikan tidak langsung terlihat, berbeda dengan penodongan atau perampokan.
Dari ketiga permasalahan itu, tampak jelas bahwa orang lebih baik bertindak permisif dan toleran daripada memulai untuk mengungkapkan korupsi atau menjadi seorang whistle blower, apalagi bila keberanian untuk jujur itu menjadi ‘senjata makan tuan’, seperti yang dialami oleh Khairiansyah sendiri. Keberanian itu taruhannya memang mahal. Tetapi bila sikap permisif lebih dibudayakan, tidakkah itu berarti kita bukan manusia atau melawan kodrat kemanusiaan kita —seperti apa yang dikatakan Shomali! Jadi, sekalipun keberanian itu mahal harganya, itu tidaklah melawan nilai alamiah (kodrat) yang kita miliki, malahan justru sejajar dengannya.
Selain itu, manusia dengan sifatnya pastilah memiliki cita-cita. Cita-cita yang merusak—lewat praktek korupsi—bukanlah cita-cita yang sejati. Itu hanyalah cita-cita yang secara kebetulan dianut, demi hasrat fisik kita semata. Oleh karena itu, tidak ada cara lain dalam menghancurkan budaya korupsi kecuali dengan cara melawan budaya permisif. Sebab, melawan budaya permisif terhadap korupsi sama halnya dengan mengedepankan salah satu nilai dalam cita-cita kemanusiaan kita, yakni nilai kejujuran. Sebagai kata akhir, peganglah diktum ini, “Hentikan budaya permisif!”***
-salah satu artikel dlm Buku "Korupsi Kemanusiaan" (Andang Listya ed.)
Kembali nge-Blog
12 tahun yang lalu


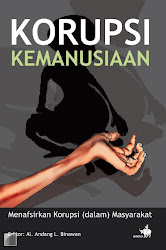





Tidak ada komentar:
Posting Komentar