Hidup ini hanyalah mampir ngombe. Semuanya terjadi begitu saja, sekadar untuk mengambil minum melepas lelah. Bagiku sama saja, hidup adalah kesempatan untuk mengambil saripati-saripati dari setiap pengalaman yang dijumpai. Mampir ngombe berarti memaknai setiap langkah yang pernah dipijak.
***
Tepatnya empat tahun yang lalu. Dalam sebuah perjalanan ke kota Surabaya aku dan seorang temanku kehabisan uang di tengah perjalanan. Baru kali ini aku pergi jauh, bahkan keluar kota. Alasan pergi ke Surabaya pun hanya ikut temanku. “Daripada be-te mendingan kita liburan ke surabaya tempat kakekku”, katanya.
Kami memutuskan untuk naik kereta. Tetapi kami tidak langsung ke Surabaya, aku tergiur ajakan temanku untuk mampir dulu di Semarang. Di situ kita jalan-jalan dulu di Simpang Lima dan lihat-lihat kota Semarang. Tentu saja aku senang dan mau saja mengikuti permintaannya, karena memang keluargaku tidak pernah mengajakku keluar kota. Aku berasal dari keluarga sederhana, sejak lahir aku tinggal di Jakarta.
Sesudah seharian jalan-jalan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini kami meneruskan dengan naik bis. Kami sudah menghitung-hitung biaya yang akan dikeluarkan. Ternyata uangnya hanya cukup untuk naik bis, dan jatah makan malam tidak ada sama sekali. Kami berharap agar kami bisa segera sampai Surabaya.
Di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi. Bis yang kami kendarai mogok. Setelah diperiksa ternyata bis ini tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan, karena mesti bongkar mesin. Padahal waktu itu tengah malam, dan berada agak di tengah hutan. Beberapa di antara penumpang memutuskan untuk tinggal di bis, menanti pagi dan melanjutkan perjalanan dengan bis lain yang lewat.
Tetapi kami berpikir lain. Kami mencoba tetap mencari bis lain malam itu. Kondektur mengembalikan sebagian uang transport, dan sambil menunggu bis yang lewat, kami berjalan kaki perlahan-lahan. Sesekali melewati kampung kecil. Baru menjelang pagi, kami memasuki sebuah desa yang cukup besar. Karena hampir sehari kami tidak makan, kami memutuskan untuk sarapan di sebuah warung. Kami tidak menyangka bahwa sisa uang setelah sarapan itu tinggal dua ribu saja. Kami bingung, dan dalam kebingungan itu kami memutuskan untuk jalan saja. Temanku mengatakan bahwa kota Surabaya sudah dekat. Mungkin sekitar 4 jam jalan kaki.
Setelah 4 jam lewat ternyata kami belum juga sampai kota Surabaya. Aku sudah merasa kecapaian begitupun temanku. Kami mencoba terus melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa tidak berapa lama lagi kami akan sampai.
Hari semakin sore, badanku sudah terasa lemah, begitupun temanku. Selama perjalanan tadi kami hanya melewati kota-kota kecil. Sempat kami bertanya ke seorang bapak mengenai seberapa jauh lagi kota Surabaya. Bapak itu mengatakan, “Tidak lama lagi, nak!”
Menurutku bapak itu menjawabnya kalau perhitungan itu dengan naik kendaraan. Sementara itu, aku benar-benar tidak kuat lagi untuk berjalan. Aku memohon pada temanku untuk berhenti sejenak melepas lelah. Bagiku ini kesempatan untuk mengumpulkan tenaga lagi. Ketika aku istirahat, mataku berkunang-kunang, terasa kecapaian. Beberapa menit kemudian, aku tidak tahan lagi untuk muntah. Temanku terkejut, dia berusaha menolong. Dia mau membelikan obat, tetapi itu tidak mungkin, karena sebelum minum obat, mestinya makan dulu, sedangkan uang tinggal dua ribu perak saja.
Dari seberang jalan, ada seorang ibu yang dari tadi memperhatikan kami. Dengan rasa ibanya, dia mendekati kami dan bertanya kepada kami. Ibu ini kelihatan sederhana sekali. Dia mau menolong kami, tetapi sepertinya tidak mungkin karena dia tampak tidak punya apa-apa. Dia berpikir sejenak dan memutuskan mengantar kami ke rumah terdekat untuk sekadar memberikan tempat yang agak layak buat istirahat kami. Sampai di rumah itu, kami diberi teh hangat. Tetapi bapak pemilik rumah itu merasa curiga dengan kami. Walaupun temanku sudah menjelaskan semua pengalaman kami seharian ini, dia tidak mengizinkan kami istirahat di situ. Bapak itu meminta ibu sederhana itu untuk mengantar kami ke ketua RT saja. Sesampai di rumah pak RT, dia berpikiran yang sama, dia lebih curiga, dan meminta kami untuk tinggal di balai desa saja. Ibu yang mengantarkan kami tadi membawa kami ke balai desa, dan setelah itu mohon pamit, karena rumahnya berada di desa tetangga. Dia sebenarnya adalah seorang buruh tani di sawah milih penduduk desa ini.
Sambil duduk beristirahat, kami mencoba berpikir apa yang bisa kami lakukan selanjutnya. Badanku sudah lemas sekali. Hari sudah mulai malam. Azan Mahgrib sudah berkumandang. Sekitar jam setengah 8 malam, seorang bapak mendekati kami. Dia bersorban putih dan memakai kopiah putih. Kami tahu bahwa bapak ini baru pulang dari Mushalla di seberang balai desa ini. Dia bertanya pada kami, mengapa kami bisa terdampar di tempat ini. Dengan rasa agak kesal kami mencoba menjawab pertanyaan bapak ini, karena kami yakin dia juga akan curiga dengan kami, dan setelahnya akan meninggalkan kami.
Tetapi, kenyataannya terjadi sebaliknya. Dia memutuskan untuk membawa kami ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, kami disambut dengan baik oleh keluarganya. Kami disajikan makanan. Setelah itu ibunya membawakan obatan ala kadarnya buatku, biar aku cepat sembuh.
Bapak itu menanyakan banyak hal tentang kami, dari mana kami, sudah kelas berapa, bahkan apa agama kami. Dalam suatu kesempatan bapak itu menceritakan mengapa penduduk di sini begitu curiga dengan orang asing. Kampung ini sudah beberapa kali kecurian. Kali lalu ada yang kecurian ayam. Sebulan yang lalu ada yang sapinya hilang. Seminggu lalu ada yang kehilangan motor. Modusnya hampir sama, mereka menumpang menginap di rumah seorang penduduk.
Tiga bulan yang lalu, ada seorang pencuri tertangkap dan pencuri itu mati dibakar massa. Kejadian ini membuat trauma masyarakat, karena beberapa orang yang terlibat pembakaran ditahan oleh polisi. Waktu itu bapak ini sempat melarang massa untuk menghakimi sendiri pencuri itu. Tetapi perjuangannya sia-sia, dan kejadian itu terlanjur terjadi. Maka dari itu, sekarang penduduk curiga dengan orang asing. Lebih baik menolak daripada mendapatkan sial.
Sehabis cerita, bapak ini mempersilahkan kami istirahat. Malam itu, dia masih melanjutkan mengajar anaknya untuk membaca Al-Quran. Bapak ini ternyata seorang ustad. Sejak awal pertemuan kami, aku merasa takut sekali untuk berbicara dengannya, karena pakaian ibadatnya yang memberikan kesan negatif padaku.
Selama tinggal di Jakarta, aku antipati dengan orang Islam. Alasan yang utama karena kebanyakan anak tetanggaku mengejek aku karena aku anak Katolik. Aku juga trauma dengan membaca beberapa berita di mana di Ambon ada perang atas nama agama, lalu di beberapa tempat ada gereja dibakar, bahkan gerejakupun sekarang tidak mendapatkan izin pembangunan. Maka dari itu aku menutup diri dari mereka.
Tetapi yang kualami sekarang ini berbeda sama sekali. Seorang Ustad, yang notabene taat beribadah dan menjalankan ajaran Islam dengan baik, memperlakukan aku yang Katolik ini dengan cara berbeda, tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Hatiku terharu. Bahkan malam itu, mereka sekeluarga tidur di ruang tamu, menemani kami. Tampaknya mereka tak layak tidur di kamar mereka sendiri, yang lebih nyaman. Mereka mengagungkan tamunya, yang jelas-jelas ‘orang lain’ bagi mereka.
Keesokan harinya setelah sarapan, kami diikutkan pada truk tetangganya yang memang hendak pergi ke Surabaya mengambil barang dagangan. Aku bersyukur sekali atas pengalaman ini. Lewat pengalaman ini sikapku terhadap orang Islam berubah. Damai tidak diciptakan dari menutup diri. Ustad ini mengajarkanku untuk mau menerima siapa saja, tanpa memandang dari agama mana atau dari suku mana. Damai justru hadir lewat terbuka bagi siapapun. Urip mung mampir ngombe. Setelah 4 tahun itu berlalu, sekarang aku justru mempunyai banyak teman dari kalangaan Islam. Kami seringkali berdialog.
Bluntas, Januari 2006
Kembali nge-Blog
12 tahun yang lalu


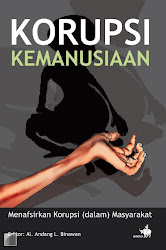






1 komentar:
Pengalaman yang menarik frat..hehe..=D
Posting Komentar