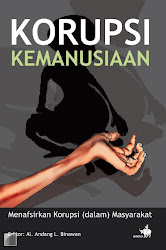Jalan menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, berlangsung seru. Ada 3 pasangan capres dan cawapres yang bertarung. Ketiga pasangan tersebut sudah promosi diri, menawarkan program-program bakal pemerintahannya, bak seperti penjual obat menawarkan dagangannya di pasar malam. Sementara itu, tim sukses juga berharap calon pasangan yang diusung bisa gol menuju istana kepresidenan.

Di sisi lain, rakyat Indonesia, yang adalah pemilih dalam pemilu tersebut, seperti dibuat bingung. Ketiga pasangan tersebut selalu menawarkan program-program yang baik, yakni program yang selalu mengatasnamakan masyarakat. Kadang-kadang pemilu ini seperti menjadi semacam pertaruhan. Janji-janji calon yang diumbar selama kurang lebih 2 bulan adalah sebuah pertaruhan untuk bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Setidaknya ada banyak penilaian dan isu yang muncul, yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih presiden dan wakil presiden kali ini. Pertama, persoalan ideologi. Dari ketiga pasangan ini, masyarakat sudah mulai bisa melihat ke arah mana negara ini akan dibawa dan dipimpin. Yang paling kentara adalah persoalan memilih antara nasionalisme atau pro-Islam. Selain itu, karena Indonesia adalah negara majemuk, dengan beragam suku dan latar belakang, persoalan daerah juga dikedepankan. Isu yang mencuat adalah soal Jawa-non jawa.
Kedua, persoalan kebijakan. Harapan besar dari masyarakat adalah pemerintahan yang benar-benar pro wong cilik. Siapapun orangnya, rakyat hanya akan memilih orang yang sungguh mau melihat keadaan rakyat dan mau memajukan bangsa. Meskipun bangsa ini sudah berumur 60 tahun lebih, pada kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tercatat dalam sebuah survey, pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi. Sekitar 30 juta rakyat, yang berada di usia kerja, sama sekali tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dengan pekerjaan yang sewajarnya.
Terlepas dari isu dan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi-lagi hal yang paling mendasar dalam pemilihan ini adalah pasangan mana yang paling cocok dan paling representatif dan mampu menjawab keinginan besar seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai analisa dari para ahli, guna menanggapi ketiga pasangan ini sudah bermunculan. Setiap hari, kita bisa melihat lewat layar kaca, membaca lewat media massa, dan mendengar lewat radio, serta berdiskusi di warung pojok, membahas calon mana yang sungguh pas di hati rakyat. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Seperti mencari emas di hamparan pasir yang begitu luas.
Kadang-kadang, masyarakat sudah jenuh juga terhadap persoalan ini. Seperti lingkaran setan yang tak pernah usai. Harapan tinggal harapan. Persoalan selalu berulang dari masa ke masa. Presiden yang terpilih tidak selalu ada dalam hati rakyat. Lalu, daripada ribut soal pilpres, yang penting bagi mereka adalah bagaimana bisa mengisi ‘perut’ mereka hari ini.
Nah, setelah kita belajar dari tokoh dan peristiwa dalam sejarah kristianitas, kita diajak untuk mengkisahkan bagaimana Allah turun menjadi manusia dalam konteks ini. Apakah Allah masih relevan ketika masyarakat kita sedang bingung memilih sosok mana yang pas. Apakah bahasa iman yang kita pelajari sesuai dengan realita dalam masyarakat? Bagaimana kita menceritakan kisah Kristus dengan tepat dalam kondisi dan situasi pilpres kali ini?
Bahasa Iman berbicara apa?
Dalam peristiwa inkarnasi, seperti yang diungkapkan dalam Yoh 3:16, “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang dipercaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal,” di situ kita bisa melihat dengan jelas, bagaimana Allah berpihak dan terlibat dalam hidup manusia. Maka, kisah Kristus dalam pilpres kali ini terkait erat dengan pemimpin mana yang sungguh(!) mau berpihak dan terlibat.
Pembelajaran lewat tokoh Maximus Confessor, menawarkan kepada kita sebuah pertimbangan dalam memilih pasangan capres-cawapres mana yang baik. Prinsipnya, jangan membawa iman ke dalam politik. Jangan menggunakan iman demi kepentingan politik. Maka dari itu, pertimbangan tentang sosok yang nasionalis adalah pertimbangan yang masuk akal. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang begitu majemuk, yang berasal dari beragam agama.
Sementara itu, Agustinus, dalam “de civitate Dei” berharap agar pemimpin itu adalah pemimpin yang realistis, yang belajar dari pengalaman. Hidup bernegara adalah “hiduplah sebaik mungkin.” Menjadi pemimipin adalah menjadi pribadi yang tahu berbuat apa bagi rakyatnya. Meskipun punya pengalaman masa lalu yang buruk, dia bisa belajar dari situ, dan mampu bertransformasi di masa yang akan datang, yakni membawa kebaikan bagi seluruh rakyat.
Anselmus menegaskan sekali lagi bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara iman dan negara. Iman dan politik adalah dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah pasangan yang menawarkan kehidupan yang benar-benar fokus pada kehidupan itu sendiri, bukan memindahkan ‘agama’ ke dalam kehidupan bernegara.
Bagi Thomas Aquinas, kebenaran itu adalah kerinduan setiap orang. Berdasarkan hal ini, program-program yang sungguh menawarkan ditegakkannya kebenaran akan menjadi opsi yang tepat bagi pemilih. Konsep ‘kebenaran’ di sini mesti tegas! Mengapa? Kita lihat sendiri, bahwa di Indonesia betapa mudahnya kebenaran diputarbalikkan. Yang korupsi, yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak malah bebas berkeliaran, sedangkan yang cuma mencuri ayam malah dibakar massa. Dunia seperti dibolak-balik.
Kebenaran itu selayaknya didasarkan pula pada dasar negara kita, yakni Pancasila dan UUD 1945. Sama seperti yang dibuat oleh Martin Luther. Dia mengajak kita ke prinsip ‘back to basic’ (sola scriptura). Sementara itu, Konsili Trente juga menekankan hal yang sama, tetapi juga menambahkan peran yang lain, yakni tradisi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, tradisi itu konkret dalam bentuk tradisi penafsiran baru (menurut situasi dan konteks zaman) atas undang-undang (misalnya amandemen UUD 1945), tanpa harus mengubah dasar negara, yang telah dicita-citakan dan dibangun oleh para founding fathers bangsa ini.
Cita-cita dan semangat pendiri negara ini adalah cita-cita yang mesti pula diteruskan oleh calon-calon pemimpin baru negara ini. Oleh karena itu, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang omongannya bisa dipercaya oleh rakyat, berbicara tegas(!) dan mampu menjawab keinginan konkret masyarakat. Konsili Vatikan I menegaskan hal itu (seperti dalam perumusan infalibilitas paus). Tetapi, pemimpin itu pun harus mawas diri. Tindakan otoriter dan sikap reaktif adalah tindakan yang paling rawan bisa dibuat oleh seorang pemimpin (kritik terhadap infalibilitas paus).
Newman menawarkan sebuah alternatif lain. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya pengalaman dengan rakyat dan mau berkembang bersama rakyat. Dan juga melandaskan alur gerak kepemimpinannya pada peranan suarahati. “Jika melawan suarahati, itu berarti bagaikan membunuh wewenang sendiri.” Maka dari itu, pemimpin haruslah melibatkan rakyat seluruhnya, bukan hanya melibatkan orang yang punya ‘duit’ saja.
Bonhoeffer menegaskan soal keterlibatan yang sungguh. Menjadi pemimpin adalah memberikan dirinya. Seperti martir, dia ‘berbuat sesuatu’ untuk kehidupan. Pemimpin harus berani melakukan sesuatu di saat-saat sulit, meskipun itu taruhannya adalah nyawa. Yang paling pokok adalah menghindari yang jahat demi kebaikan banyak orang.
Lewat Konsili Vatican II, prinsip aggiornamento menjadi penting. Bertindak sebagai pemimpin adalah bertindak sebagai pribadi yang mau terbuka terhadap siapapun, bisa menjadi fasilitator bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan beberapa kelompok saja.
Dan yang terakhir, Tissa Balasuriya. Kontekstual! Bahasa pemimpin adalah bahasa yang hidup dalam rakyat. Maka dari itu, pemimpin haruslah bisa membaca situasi dan konteks Indonesia secara keseluruhan.
Penutup
Melalui butir-butir di atas, bahasa iman kita tampak menjadi begitu aktual, mampu menjawab kebutuhan orang beriman, di sini dan saat ini. Pun juga inspiratif, karena mau melibatkan semakin banyak orang dalam sejarah keberlangsungan manusia. Dengan pembahasan tentang pilpres 2009 tadi, kita sebagai orang beriman jelas-jelas diajak untuk terlibat, sebagaimana Yesus, 2000 tahun yang lalu, yang sungguh terlibat dalam hidup manusia!***
Read More...

Di sisi lain, rakyat Indonesia, yang adalah pemilih dalam pemilu tersebut, seperti dibuat bingung. Ketiga pasangan tersebut selalu menawarkan program-program yang baik, yakni program yang selalu mengatasnamakan masyarakat. Kadang-kadang pemilu ini seperti menjadi semacam pertaruhan. Janji-janji calon yang diumbar selama kurang lebih 2 bulan adalah sebuah pertaruhan untuk bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Setidaknya ada banyak penilaian dan isu yang muncul, yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih presiden dan wakil presiden kali ini. Pertama, persoalan ideologi. Dari ketiga pasangan ini, masyarakat sudah mulai bisa melihat ke arah mana negara ini akan dibawa dan dipimpin. Yang paling kentara adalah persoalan memilih antara nasionalisme atau pro-Islam. Selain itu, karena Indonesia adalah negara majemuk, dengan beragam suku dan latar belakang, persoalan daerah juga dikedepankan. Isu yang mencuat adalah soal Jawa-non jawa.
Kedua, persoalan kebijakan. Harapan besar dari masyarakat adalah pemerintahan yang benar-benar pro wong cilik. Siapapun orangnya, rakyat hanya akan memilih orang yang sungguh mau melihat keadaan rakyat dan mau memajukan bangsa. Meskipun bangsa ini sudah berumur 60 tahun lebih, pada kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tercatat dalam sebuah survey, pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi. Sekitar 30 juta rakyat, yang berada di usia kerja, sama sekali tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dengan pekerjaan yang sewajarnya.
Terlepas dari isu dan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi-lagi hal yang paling mendasar dalam pemilihan ini adalah pasangan mana yang paling cocok dan paling representatif dan mampu menjawab keinginan besar seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai analisa dari para ahli, guna menanggapi ketiga pasangan ini sudah bermunculan. Setiap hari, kita bisa melihat lewat layar kaca, membaca lewat media massa, dan mendengar lewat radio, serta berdiskusi di warung pojok, membahas calon mana yang sungguh pas di hati rakyat. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Seperti mencari emas di hamparan pasir yang begitu luas.
Kadang-kadang, masyarakat sudah jenuh juga terhadap persoalan ini. Seperti lingkaran setan yang tak pernah usai. Harapan tinggal harapan. Persoalan selalu berulang dari masa ke masa. Presiden yang terpilih tidak selalu ada dalam hati rakyat. Lalu, daripada ribut soal pilpres, yang penting bagi mereka adalah bagaimana bisa mengisi ‘perut’ mereka hari ini.
Nah, setelah kita belajar dari tokoh dan peristiwa dalam sejarah kristianitas, kita diajak untuk mengkisahkan bagaimana Allah turun menjadi manusia dalam konteks ini. Apakah Allah masih relevan ketika masyarakat kita sedang bingung memilih sosok mana yang pas. Apakah bahasa iman yang kita pelajari sesuai dengan realita dalam masyarakat? Bagaimana kita menceritakan kisah Kristus dengan tepat dalam kondisi dan situasi pilpres kali ini?
Bahasa Iman berbicara apa?
Dalam peristiwa inkarnasi, seperti yang diungkapkan dalam Yoh 3:16, “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang dipercaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal,” di situ kita bisa melihat dengan jelas, bagaimana Allah berpihak dan terlibat dalam hidup manusia. Maka, kisah Kristus dalam pilpres kali ini terkait erat dengan pemimpin mana yang sungguh(!) mau berpihak dan terlibat.
Pembelajaran lewat tokoh Maximus Confessor, menawarkan kepada kita sebuah pertimbangan dalam memilih pasangan capres-cawapres mana yang baik. Prinsipnya, jangan membawa iman ke dalam politik. Jangan menggunakan iman demi kepentingan politik. Maka dari itu, pertimbangan tentang sosok yang nasionalis adalah pertimbangan yang masuk akal. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang begitu majemuk, yang berasal dari beragam agama.
Sementara itu, Agustinus, dalam “de civitate Dei” berharap agar pemimpin itu adalah pemimpin yang realistis, yang belajar dari pengalaman. Hidup bernegara adalah “hiduplah sebaik mungkin.” Menjadi pemimipin adalah menjadi pribadi yang tahu berbuat apa bagi rakyatnya. Meskipun punya pengalaman masa lalu yang buruk, dia bisa belajar dari situ, dan mampu bertransformasi di masa yang akan datang, yakni membawa kebaikan bagi seluruh rakyat.
Anselmus menegaskan sekali lagi bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara iman dan negara. Iman dan politik adalah dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah pasangan yang menawarkan kehidupan yang benar-benar fokus pada kehidupan itu sendiri, bukan memindahkan ‘agama’ ke dalam kehidupan bernegara.
Bagi Thomas Aquinas, kebenaran itu adalah kerinduan setiap orang. Berdasarkan hal ini, program-program yang sungguh menawarkan ditegakkannya kebenaran akan menjadi opsi yang tepat bagi pemilih. Konsep ‘kebenaran’ di sini mesti tegas! Mengapa? Kita lihat sendiri, bahwa di Indonesia betapa mudahnya kebenaran diputarbalikkan. Yang korupsi, yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak malah bebas berkeliaran, sedangkan yang cuma mencuri ayam malah dibakar massa. Dunia seperti dibolak-balik.
Kebenaran itu selayaknya didasarkan pula pada dasar negara kita, yakni Pancasila dan UUD 1945. Sama seperti yang dibuat oleh Martin Luther. Dia mengajak kita ke prinsip ‘back to basic’ (sola scriptura). Sementara itu, Konsili Trente juga menekankan hal yang sama, tetapi juga menambahkan peran yang lain, yakni tradisi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, tradisi itu konkret dalam bentuk tradisi penafsiran baru (menurut situasi dan konteks zaman) atas undang-undang (misalnya amandemen UUD 1945), tanpa harus mengubah dasar negara, yang telah dicita-citakan dan dibangun oleh para founding fathers bangsa ini.
Cita-cita dan semangat pendiri negara ini adalah cita-cita yang mesti pula diteruskan oleh calon-calon pemimpin baru negara ini. Oleh karena itu, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang omongannya bisa dipercaya oleh rakyat, berbicara tegas(!) dan mampu menjawab keinginan konkret masyarakat. Konsili Vatikan I menegaskan hal itu (seperti dalam perumusan infalibilitas paus). Tetapi, pemimpin itu pun harus mawas diri. Tindakan otoriter dan sikap reaktif adalah tindakan yang paling rawan bisa dibuat oleh seorang pemimpin (kritik terhadap infalibilitas paus).
Newman menawarkan sebuah alternatif lain. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya pengalaman dengan rakyat dan mau berkembang bersama rakyat. Dan juga melandaskan alur gerak kepemimpinannya pada peranan suarahati. “Jika melawan suarahati, itu berarti bagaikan membunuh wewenang sendiri.” Maka dari itu, pemimpin haruslah melibatkan rakyat seluruhnya, bukan hanya melibatkan orang yang punya ‘duit’ saja.
Bonhoeffer menegaskan soal keterlibatan yang sungguh. Menjadi pemimpin adalah memberikan dirinya. Seperti martir, dia ‘berbuat sesuatu’ untuk kehidupan. Pemimpin harus berani melakukan sesuatu di saat-saat sulit, meskipun itu taruhannya adalah nyawa. Yang paling pokok adalah menghindari yang jahat demi kebaikan banyak orang.
Lewat Konsili Vatican II, prinsip aggiornamento menjadi penting. Bertindak sebagai pemimpin adalah bertindak sebagai pribadi yang mau terbuka terhadap siapapun, bisa menjadi fasilitator bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan beberapa kelompok saja.
Dan yang terakhir, Tissa Balasuriya. Kontekstual! Bahasa pemimpin adalah bahasa yang hidup dalam rakyat. Maka dari itu, pemimpin haruslah bisa membaca situasi dan konteks Indonesia secara keseluruhan.
Penutup
Melalui butir-butir di atas, bahasa iman kita tampak menjadi begitu aktual, mampu menjawab kebutuhan orang beriman, di sini dan saat ini. Pun juga inspiratif, karena mau melibatkan semakin banyak orang dalam sejarah keberlangsungan manusia. Dengan pembahasan tentang pilpres 2009 tadi, kita sebagai orang beriman jelas-jelas diajak untuk terlibat, sebagaimana Yesus, 2000 tahun yang lalu, yang sungguh terlibat dalam hidup manusia!***