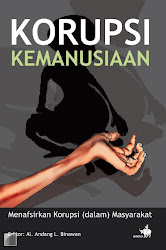Manusia dan dunia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia hidup di dunia dan dunia menghidupi manusia. Seperti dua sisi pada keping mata uang, keduanya hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Mungkin, kita seringkali membayangkan bahwa manusialah yang aktif, sedangkan dunia adalah yang pasif, yang selalu dipengaruhi oleh keaktifan manusia. Tapi ini hanyalah sebuah kamuflase (keaktifan manusia hanya diartikan sebagai yang bergerak dan dapat ditangkap dengan indera). Padahal sebenarnya duniapun bergerak dan terus berubah, tapi itu tidak mudah ditangkap oleh indera. Sejarah dan kebudayaan yang berubah merupakan pertanda bahwa dunia terus bergerak.

Dunia yang bergerak ini tentunya akan selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Maka, tidak ada manusia yang bisa berlari dari dunia (fuga mundi) semasa hidupnya. Sekalipun ada kelompok yang mengakui diri sebagai kelompok yang menyingkir dari dunia, mereka tidak sadar bahwa tetap masih hidup di dunia, dan dunia menghidupi mereka.
Demikianpun yang dialami oleh iman manusia. Iman tidak bisa lepas dari dunia. Hubungan kita dengan Allah, erat atau renggangkah, tergantung pada situasi dunia. Hubungan manusia dengan Tuhan pada zaman batu akan berbeda dengan manusia pada zaman mesin industri. Maka dari itu, cara pengungkapannya, tuntutan-tuntutan dan tantangannya pun berbeda-beda.
Tulisan ini akan memfokuskan pada topik tentang iman manusia di zaman mesin industri. Pada zaman mesin industri ini, segala teknologi telah mengubah wajah bumi. Dunia khayal yang diangan-angankan telah menjadi kenyataan. Mata telanjang manusia diperjelas daya lihatnya melalui sinar-X dan mikroskop elektronik. Otot-otot manusia diperkuat tenaganya dengan segala macam bentuk mesin. Tampaknya, dari hari ke hari manusia merasa segambar dengan sifat-sifat Allah. Dengan kemajuan teknologi, manusia secara samar-samar merasa banyak tahu, merasa bisa membuat ini-itu, merasa berkuasa.
Ini tentunya sangat mempengaruhi iman manusia terhadap Tuhan. Perhatian manusia mulai bergeser. Ada suatu keyakinan bahwa segala hal yang dulunya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang dulunya jauh mengawang-awang, karena hanya Tuhanlah yang bisa, kini dengan mudah dijumpai di depan mata. Eksistensi Tuhan digeser dengan dunia ini, di sini dan sekarang. Iman manusia mendapatkan tantangannya. Iman manusia menghadapi kenyataan dunia sekuler. Lalu bagaimanakah sikap iman terhadap tantangan ini? Bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijawab, karena dengan demikian mesti melihat secara keseluruhan, baik dari sisi iman sendiri, maupun dari sisi sekularisasi (dan sekularisme)-nya. Ini adalah bagian dari sejarah manusia, jadi manusialah yang harus menjawab tantangan ini.
Apa itu Iman?
Menurut tradisi Kristen, iman dilukiskan sebagai serah diri, yaitu manusia yang menyerahkan seluruh dirinya dan hidupnya secara bebas (tidak karena terpaksa, melainkan dengan sukarela), dengan budi dan hatinya tunduk kepada kehendak Allah yang mewahyukan. Manusia yang berkata “ya” kepada Allah, bukanlah hanya ucapan bibir saja. “Ya” berarti pembaktian hidup.
Kata bebas yang digambarkan di atas, tidak hanya berarti bebas dalam hal fisik, berpikir dan bebas mengambil keputusan menurut keyakinannya sendiri, melainkan lebih mengikuti suara hati dan menentukan arah hidup sendiri. Dengan bebas manusia memasuki kemerdekaan anak-anak Allah, yakni kemerdekaan seseorang yang dibebaskan dari segala rasa takut dan merasa diri aman dalam tangan dan kasih Allah. Kasih Allah menembus rasa takut. Maka dari itu, iman membebaskan karena memecahkan belenggu ketakutan dan kecurigaan.
Tetapi, kadangkala sifat yang menyeluruh dari iman sulit dimengerti oleh pandangan yang rasional. Padahal rasionalitas adalah unsur hakiki dalam kehidupan manusia. Maka, perlu penjelasan yang matang bagaimana iman itu pun dapat ditangkap tidak hanya oleh hati, melainkan juga oleh budi kita. Ditelusuri lebih dalam, iman merupakan sebuah sikap, maka rasionalitas iman pertama-tama menyangkut motivasi atau alasannya: Mengapa manusia percaya dan menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan, yang tentunya didasarkan pada pengalaman hidup setiap manusia, yang sifatnya unik dan khusus?
Iman adalah rahmat Tuhan. Dalam perkara iman, Allah berprakarsa lebih dulu. Iman tidak buta, melainkan hidup. Maka, manusia bisa mencapai sikap beriman, karena pengalaman akan Allah dalam hidupnya. Tanpa sebuah pengalaman akan Allah, sulit dipahami bagaimana seseorang bisa berserah diri, tanpa tahu siapa yang menjadi tempat penyerahan dirinya. Dengan demikian, terjawablah bagaimana iman itu diakui dalam hati dan budi.
Apa itu Sekularisasi?
Sekularisasi adalah proses yang membangun fakta dan kebenaran bahwa dunia bukanlah Tuhan dan bukanlah yang ilahi, maka manusia harus memisahkan diri dari-Nya dan mempercayakan diri pada kemanusiaannya. Di dalam dunia, manusia bukanlah obyek, tetapi subyek dan tujuan. Kapasitas manusia bukanlah hanya mengerti dunia saja, tapi juga mampu mengubahnya. Dunia telah berpindah dari tangan Tuhan ke tangan manusia.
Sekularisasi menggeser pusat dan minat manusia dewasa ini dari hidup akhirat kepada hidup ini. Manusia lebih mempedulikan hal-hal yang fana daripada hal-hal yang baka. Masalah-masalah seperti perdamaian, keadilan, kemiskinan, ekologi, pendidikan, dan pengendalian penduduk lebih menjadi pusat perhatian manusia modern daripada masalah keselamatan abadi. Intinya, yang riil dan berarti hanyalah dunia, sedangkan yang lain hanyalah khayalan manusia.
Perlu diperhatikan bahwa sekularisasi sama sekali tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi lebih pada suatu pembedaan antara bidang-bidang keagamaan dengan dunia. Penjelasan yang telah disebutkan di atas, ingin menunujukkan keotonoman manusia dan dunia sebagai tempat tinggalnya. Atau dengan kata lain, sekularisasi adalah dunia yang otonom, yang dibangun oleh manusia, yang tidak menunjukkan kerajaan Allah, tapi kerajaan manusia.
Sedangkan sekularisme adalah suatu ideologi bahwa dunia ini sebagai keseluruhan hanya dapat dimengerti tanpa hubungan apapun dengan suatu penyebab di luarnya (Sang Penciptanya). Dunia ini dapat dibangun tanpa harus mempedulikan hal-hal yang transenden. Inilah suatu close world view yang menyangkal adanya Sang Pencipta. Dalam sekularisme, iman kepada Tuhan tidak memiliki tempat karena tidak dibutuhkan lagi.
Tampak bahwa ada hubungan antara sekularisasi dan sekularisme. Sekularisasi bisa dilihat secara positif, sedangkan sekularisme lebih bermakna negatif. Tapi sekularisasi bisa menjadi suatu proses menuju sekularisme.
Bagaimana Hubungan antara Iman dan Sekularisasi (atau juga sekularisme)?
Pertama-tama, akan dilihat dari sudut sekularisasi yang memandang iman. Sekularisasi melihat iman yang ada dalam agama sebagai hal yang lebih berminat kepada hidup yang lain, dunia yang lain, dan waktu yang lain. Maka harus diadakan pembedaan antara dunia yang nyata-profan, dengan dunia lain yang suci dan keramat (agama). Bagi kebanyakan orang dalam dunia sekuler, kegiatan dalam keagamaan yang menyangkut iman adalah sebuah kegiatan yang tidak real (misalnya, sembah sujud, perayaan liturgis) dibandingkan dengan kegiatan duniawi (sekuler). Demikianpun juga dalam bidang kebudayaan dan pengetahuan, pengetahuan sekuler adalah pengetahuan yang diperoleh dengan usaha manusia, melalui pendayagunaan daya-daya intelektual alami manusia yang berupa pengamatan, pengingatan dan penalaran. Tampak bahwa semuanya bergantung pada hal-hal yang empiris.
Di dalam dunia sekuler manusia dipandang berotonomi. Kalaupun referensi samar-samar kepada Allah diperbolehkan, sebenarnya tidak ada pengakuan real terhadap hal yang lebih tinggi dari manusia. Mentalitas manusia sekuler sama sekali tidak mendukung orang mencapai iman kepercayaan. Mereka yang memilih untuk beriman akan berenang dengan kuat melawan arus kuat persuasi manusia, sebab iman dalam zaman ini barangkali akan kelihatan sebagai peninggalan masa lalu saja.
Sama halnya dalam sekularisme, tetapi lebih parah lagi, karena menisbikan iman dan agama. Dalam sekularisme, keyakinan dan nilai-nilai keagamaan samasekali tidak boleh berperan. Mereka melihat bahwa iman hanya mempedulikan Allah dan tidak mempedulikan manusia sama sekali. Maka, semuanya harus dinilai, diatur, dikerjakan tanpa sama sekali mengindahkan suatu realitas adi-kodrati, artinya yang melampaui batas-batas dunia.
Kedua, iman yang memandang sekularisasi (sekularisme). Untuk memahami setepat mungkin sikap iman terhadap sekularisasi, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sasaran yang hendak dicapai kedua pihak. Dari uraian sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai sekularisasi pada dasarnya adalah manusia yang otonom (berdaulat). Sedangkan tujuan iman dalam agama adalah memanusiakan manusia sebagai pribadi yang berdaulat (sama seperti sekularisasi). Tetapi berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang ada, perbedaannya terletak pada cara kerjanya. Sekularisasi semata-mata menggunakan bukti empiris yang tersedia di dunia ini. Sedangkan iman dalam agama mendayagunakan kekuatan supra-empiris yang datang dari dunia lain. Sebelum masa Fajar Budi, perbedaan cara kerja ini bergabung dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan agama. Namun sesudahnya, menjadi dua kekuatan yang terpisah, bahkan sebagai dua gerakan yang saling berlawanan. Dari kenyataan ini, menjadi jelas bahwa sikap iman dalam agama terhadap sekularisasi bersikap mendua, antara mendukung dan menentang. Sikap mendukung dapat dilihat dari segi pengajarannya. Iman berusaha menjelaskan ajarannya secara rasional dengan bantuan filsafat dan ilmu pengetahuan empiris. Sedangkan sikap menolak, terutama menolak cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dianggap membahayakan ortodoksi serta kewibawaan. Apalagi sikap sekularisme yang menisbikan eksistensi Tuhan, iman akan menolaknya dengan tegas.
Sebuah Refleksi: Bagaimana menyikapinya?
Sudah diungkapkan pada awal tulisan bahwa manusia dan dunia berjalan berdampingan dan saling mempengaruhi. Antara keduanya telah menjadi bagian dan tidak bisa dipisahkan. Maka, yang ada hanya dukungan atau pertentangan (bukan pemisahan). Begitupun dengan iman, sekalipun ada pertentangan, yang menimbulkan corak negatif bagi hubungan manusia dengan Tuhan, tetap ada aspek positif di dalamnya.
Pertama, bisa dikatakan, sebagai tantangan. Dengan adanya tantangan, iman yang sebelumnya biasa-biasa saja, pasif (tidak ada hambatan), dibangkitkan lagi dan dipertanyakan lagi visinya. Sebagai contoh, pengalaman-pengalaman generasi muda ketika mewarisi iman dari orangtua mereka. Iman mereka bisa hanya jatuh pada suatu pengajaran atau pemahaman dan teori saja. Ini suatu iman permukaan atau bahkan suatu pendangkalan. Justru dengan adanya tantangan, seluruh daya-jiwa mereka digerakkan, dan mau tidak mau, iman mereka dibangkitkan atau bahkan dipertanyakan. Karena adanya tantangan, mereka mendapatkan pengalaman, terutama pengalaman akan Tuhan (iman mereka dikuatkan).
Kedua, dengan adanya tantangan, terkhusus tantangan iman dalam dunia sekular, mesti akan muncul pertanyaan, mengapa terjadi perubahan dunia menuju sekular? Ini adalah tanda-tanda zaman. Dengan pertanyaan ini, kita akan berefleksi dan diajak untuk bersikap dengan baik dan bijaksana. Kita akan menemukan sebab musabab terjadinya sekularisasi, yang pada dasarnya terjadi di dalam Kekristenan Eropa pada zaman Fajar Budi, di mana pada saat itu manusia mulai menemukan banyak hal, dan sesuatu yang tidak mungkin telah menjadi mungkin bagi manusia. Segala yang jauh sebenarnya ada dan nyata di hadapan manusia. Sebaliknya, iman pada waktu itu tidak menjawab sama sekali kebutuhan manusia karena terlalu adi-kodrati, transenden atau bahkan bersifat mistis saja. Akhirnya, iman mulai dipisahkan atau bahkan ditinggalkan.
Apakah dengan kenyataan ini, iman (yang ada di dalam agama) memusuhi dunia, yang telah mengkhianatinya. Bukan suatu tindakan yang bijaksana. Inilah suatu tanda-tanda zaman, yang pada intinya ingin menggerakkan iman ke arah yang lebih maju lagi, sejajar dan berdampingan dengan dunia sekular. Lalu, bagaimanakah caranya? Konsili Vatican II telah menjawabnya. Gaudium et Spes adalah cerminan sebuah jawaban yang menanggapi kenyataan dunia dewasa ini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang adalah juga milik murid-murid Kristus. Berikutnya, ini menandakan dimulainya suatu dialog (aggiornamento terus-menerus) antara iman Kristiani dengan dunia sekular. Dialog ini terjadi bukan karena ada sesuatu yang berharga dari iman yang ingin dikatakan pada dunia, melainkan iman Kristiani harus memperhatikan diri mereka di tengah-tengah realita yang ada, bukan malahan tertutup dengan sekularisasi. Lebih jauh, dialog ini adalah dialog dua sisi, di mana keduanya tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami. Dialog ini juga tidak hanya teori, interpretasi, tapi juga harus sampai ke level kerjasama.
Mungkin akan sulit membayangkan dialog seperti apa itu sebenarnya. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan yang berdialog dengan iman. Produk-produk yang dihasilkan olehnya hendaknya diarahkan kepada kebutuhan manusia, bukan malahan sebaliknya, manusia dijadikan budak (misalnya TV, komputer, dsb). Ini maksudnya adalah semata-mata demi hari depan manusia juga. Cara pandang yang positif ini, muaranya akan membawa manusia kepada kesadaran bahwa Allah ada di dalam segala, dan segala ada di dalam Allah (Allah yang konkret).
Ketiga, menanggapi aspek-aspek negatif dari sekularisasi atau bahkan sekularisme, sebenarnya iman manusia saat ini berada dalam suatu proses pemurnian. Pada paragraf pertama refleksi ini, telah diungkapkan sebagian. Jelasnya, saat ini manusia berada dalam tahap krisis. Krisis bukanlah suatu hal yang negatif, justru suatu hal yang mencoba memurnikan. Perlu dipahami bahwa akibat-akibat sekularisasi yang tidak diinginkan hanyalah akibat-akibat samping saja. Akibat samping itu bukan kesalahan proses sekularisasi itu sendiri, melainkan kesalahan manusia yang tak mau atau tak mampu menanggapinya. Misalnya kemiskinan, sebenarnya ini terjadi karena jarak antara mereka yang berpengetahuan dan berketerampilan lebih serta mereka yang hanya berpengetahuan dan berketerampilan sedikit makin lama makin lebar; hanya mereka yang mempunyai dana yang bisa mempunyai kesempatan. Akibat selanjutnya, yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Muncullah pula pemahaman bahwa agama adalah candu, seperti yang diungkapkan Marx (yang juga mengusahakan perjuangan kelas) dan ‘Tuhan sudah mati’ oleh Nietsche. Ada semacam ketidakmampuan dan sikap pesimistis dari manusia.
Maka dari itu, kita mesti menyadari bahwa menjadi manusia dan mengalami kepenuhan sesudahnya adalah suatu proses. Ini adalah salah satu cara Tuhan dalam mewahyukan dirinya, dan memang cara ini merupakan suatu misteri. Maka perlu waspada terhadap penggambaran yang salah terhadap Allah, karena melalui inilah manusia mudah menjadi salah dalam menafsirkan realita yang ada.
Dan yang keempat, perlu dihindari segala perhatian yang hanya dipusatkan pada agama (aspek ritual) saja. Padahal agama, dengan segala peraturan dan kegiatannya, hanya merupakan sarana dan jalan memperkuat dan menyokong iman, yang harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Yang pokok bukan agama, melainkan iman sebagai sikap dan orientasi dasar. Yang penting bukan iman yang formalitas, melainkan iman sebagai dasar dan dorongan hidup yang nyata, sebagai sikap dasar, dan sebagai sumber kehidupan.
Dengan demikian akan terjawablah tantangan dunia sekular itu dengan sikap baik dan bijaksana.***
Read More...