Sungguh menyebalkan! Beginilah resiko naik kereta turun di stasiun Tawang dan pas hujan deras. Bukannya disambut dengan suasana yang segar karena bisa liburan pulang ke rumah, tetapi malah dihadang oleh kekalutan kota tua, yang tiba-tiba menjadi seperti kolam kubangan raksasa.
Pagi itu, kira-kira pukul 4, aku tiba di kota kelahiranku. Sudah hampir 2 tahun ini aku tak sempat pulang ke rumah. Ada banyak alasan. Entah karena banyak kerjaan di Jakarta, entah banyak masalah, ataupun rasa enggan menghamburkan uang tabungan. Namun, karena sudah untuk sekian kalinya mama memintaku untuk liburan, maka kali ini aku pun mau menurutinya.
Seperti biasanya, para tukang becak langsung menyerbu masuk ke peron, menawarkan diri untuk membawakan barang bawaan.
“Mas, mau ke mana?” “Di luar banjir, naik becak, Mas!” “Mau diantar ke mana, Mas?” Sebegitu banyaknya orang yang menawarkan jasa untuk mengantarkan penumpang keluar dari stasiun ini. Semua orang ditawari. Mau tidak mau, semua pasti akan menggunakan jasa mereka. Tidak ada pilihan lain. Kecuali mereka yang dijemput keluarga. Tapi, aku tidak!

Aku sebenarnya benci dengan suasana seperti ini. Apalagi, sangkaku, sebagian besar mereka itu bukanlah orang yang baik-baik. Siapa yang tidak tahu kawasan kota tua semarang? Di beberapa tempat, di malam hari, menjadi daerah yang sangat rawan. Aku yakin mereka adalah bagian kehidupan kota tua yang sangar itu.
Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah minta papa untuk menjemput. Tapi, dia tidak bisa. Kakinya sakit, asam uratnya lagi kambuh. Maka, aku harus memilih salah satu dari mereka.
“Ke Dr. Cipto berapa, Pak?”
“Biasa, Mas! 10 ribu saja!”
“Ah, koq mahal amat… 5 ribu saja. khan cuma dekat situ… gak ada 1 km.”
“Ini khan hujan, Mas… jalannya sulit, air tergenang di mana-mana.”
“Pokoknya kalo tidak 5 ribu, saya tidak mau.” Aku berpaling, sambil mencoba mencari-cari becak yang lain.
“Mari, Mas!” sebegitu cepatnya bapak tadi menarik tasku, dan kemudian mempersilakan aku naik ke becaknya.
Aku begitu senang, karena penawaranku diterimanya. Tak lama kemudian, kayuhan bapak itu mulai menggerakkan roda becak. Sementara aku menikmati ketenangan karena terhindar dari air, aku mengajak ngobrol bapak tadi.
“Kalo boleh tahu, Bapak orang mana ya?”
“Saya itu orang Salatiga. Keluarga saya ada di sana,” jawabnya.
“Lha, bapak apa tidak pernah pulang ke rumah?”
“Sesekali saja pulang. Biasanya hari sabtu malam. Tapi, itu tidak tentu. Tergantung penghasilannya berapa setelah kerja seminggu. Sayang kalo uangnya habis untuk ongkos bis.”
“Putra bapak berapa?”
“Saya punya 4 anak. Yang besar kelas 1 SMA. Yang kedua kelas 2 SMP. Yang satunya kelas 4 SD dan yang kecil masih umur 3 tahun.”
“Bapak, di Semarang tinggal di mana?”
“Boro-boro punya kontrakan, Mas. Untuk makan harus menyisihkan uang secukupnya. Kalo tidak seperti itu, bagaimana saya bisa bawa uang untuk keluarga.”
“Lho, terus tidurnya di mana?”
“Tergantung. Tapi biasanya saya tidur di stasiun. Di atas becak sudah nyaman koq.”
“Ini becak Bapak, bukan ya?”
“Bukan! Ini becak juragan. Per hari saya mesti setor 10 ribu.”
Tak terasa, kayuhan becak bapak tadi sudah mengantar aku persis di depan gang masuk rumahku. Aku minta diturunkan di depan portal saja, karena memang tidak mungkin untuk menerobos masuk. Biasanya portal baru dibuka oleh penjaga sekitar jam 6 pagi. Aku ambil uang 10 ribuan, dan kuberikan ke bapak itu.
“Ini kembaliannya, Mas!”
“Gak usah, Pak! Ambil saja semuanya!”
“Maturnuwun!”
“Sama-sama, Pak!”
***
Seharian aku tidak beranjak dari tempat tidur. Papa-mama senang sekali melihat kedatanganku. Seperti pucuk dicinta, ulam tiba. Kerinduan mereka benar-benar terobati. Mereka inginnya siang tadi aku sudah bangun dan ingin bertanya banyak tentang apa saja kegiatanku selama ini di Jakarta. Tapi aku tak begitu peduli. Aku tetap saja di dalam kamar. Namun sore ini, aku dipaksa bangun oleh mama. Kebetulan ini Sabtu sore.
“Ayo ke Gereja. Papa-mama dan adikmu akan ke Gereja sore ini, soalnya besok siang ada undangan mantenan di PRPP.”
Berat rasanya untuk melepas bantal. Apalagi, di Jakarta aku juga jarang pergi ke gereja. Bagaimana mau pergi ke gereja? Kadang hari sabtu saja aku masih di kantor. Hari minggu sepertinya benar-benar barang langka yang sayang untuk dibuang, kecuali untuk bermalas-malasan di tempat kos.
“Ayo, 15 menit lagi, papa sudah mau jalan lho!”
Mendengar suara terakhir dari mama, sedetik aku berpikir.
“Iya, ya! Mending aku berangkat ke Gereja saja. Supaya mama tidak bertanya-tanya soal apakah aku sering ke Gereja atau tidak selama di Jakarta.” Selama ini aku memang selalu bersilat lidah dengan mama lewat telpon. Aku selalu mengatakan bahwa aku tidak pernah lupa ke gereja. Padahal kalau dihitung-hitung, mungkin selama 2 tahun ini aku ke gereja cuma 10 kali.
***
Baru saja aku selesai doa sehabis menerima komuni, tiba-tiba mataku tertabrak dengan sesosok pria yang sedang berjalan persis di samping barisan bangkuku. Aku masih ingat. Rasanya belum lama ketemu bapak ini. Iya, benar! Persis baru tadi pagi aku ketemu bapak ini. Dia tukang becak yang mengantarku dari stasiun.
Setelah berkat penutup, aku bergegas keluar Gereja dan mencari Bapak itu. Aku mencari ke sana-ke mari. Sampai akhirnya aku menemukan Bapak tadi persis berada di dekat pintu gerbang Gereja. Aku mendekat ke sana.
“Pak, masih ingat saya?”
“Masih koq, Dik! Khan baru pagi tadi kita ketemu”
“Lho, bapak ke Gereja ya?”
“Iya, saya orang Katolik. Sudah dua bulan ini saya banyak membantu di Gereja setiap sabtu sore. Saya ikut misa, sekalian membantu satpam untuk jaga parkir. Cari uang tambahan sedikit. Tapi, setelah semua selesai, nanti saya langsung ke Salatiga. Sudah 3 minggu saya tidak pulang.”
“Kalo boleh tahu, nama Bapak siapa?”
“Nama saya Pak Harno! Lha adik namanya siapa?”
“Panggil saja saya Widi, Pak!” Tiba-tiba mama memanggilku untuk segera masuk ke mobil.
“Ok, Pak. Sampai ketemu lagi,” sapaku kepada pak Harno.
Ketika mobilku sampai di portal persis di depan pak Harno, Aku memberikan 2 lembar uang kertas, 10 ribu untuk parkir dan 50 ribu langsung kuberikan ke Pak Harno.
“Ini untuk bapak. Buat oleh-oleh untuk keluarga di Salatiga. Salam ya, Pak!”
Dalam perjalanan pulang aku merenung. Seorang Pak Harno yang telah bekerja begitu berat dan keras, nyatanya dia masih tetap setia untuk pergi ke Gereja, mengikuti Ekaristi, dan bertemu Tuhan. Sungguh berbeda dengan aku. Karena alasan capek bekerja, aku lebih sering tidak pergi ke Gereja. Untuk satu hal ini aku masih berhutang pada Pak Harno. Minggu depan, kalo bertemu lagi, aku akan bertanya, rumahnya di Salatiga di sebelah mana. Toh Semarang-Salatiga tidak jauh. Sekali-kali aku akan main ke sana.***
Semarang, Januari 2011


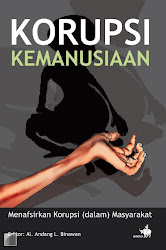








Tidak ada komentar:
Posting Komentar