
Kali ini mataku dibuka lebih lebar lagi. Serikat mengutusku untuk semakin mengenal duniaku (mengalami dan melatih diri). Probasi ini telah berkata lain dibandingkan 2 probasi luar yang terdahulu. Dunia memang terus berjalan bahkan berlari dan berpacu, tetapi aku tidak melihatnya dari sisi keindahan, ketenangan, kenyamannya, seperti yang kualami sebelumnya. Sekalipun Perigrinasi telah menunjukkan dari sisi lain, namun baru saat ini aku merasakan pengenalan yang lengkap akan duniaku. Aku tidak berani menyatakan bahwa aku sudah ahli tentang dunia ini, lebih daripada aku berani menyatakan bahwa inilah duniaku (di mana aku hidup di dalamnya), inilah realita di hadapanku.
Aku diutus ke tengah-tengah serigala, di antara kehidupan keras para buruh bangunan. Aku tidak ingin terilusi oleh istilah “Ibu Tiri tidak sekejam Ibukota”, tapi aku ingin sungguh mengalami bagian dunia lain yang dipandang dari sisi ketidakamanannya.
Selepas dari Kanisius, dengan bekal kehendak kuat, bersama teman perutusanku, kupanggul tas besar di pundakku. Aku tahu bahwa di terminal Senen banyak copetnya, tapi mau bagaimana? Ini duniaku dan aku mesti melewatinya agar aku sampai tujuanku.
Kutatap wajah anak kecil, yang mencoba bernyanyi dengan suara parau dan hanya mengandalkan bebunyian dari kumpulan tutup botol. Kasihan sekali! Aku hanya diam, tak memberikan uang sepeserpun, kecuali berpikir bahwa mereka sebenarnya hanya diperalat oleh sekelompok orang. Dan, aku merinding melihat eks-napi mabuk naik ke bis yang hanya untuk menodong (dengan cara halus). Aku tak bisa berlagak seperti Superboy, yang menyelamatkan orang-orang dan meninju mereka keluar bis, kecuali aku semakin yakin bahwa inilah duniaku.
Turun dari bis, di kanan-kiri jalan, masih ada banyak genangan air, sisa dari banjir kemarin. Bermaksud ingin menyeberangi sungai, ternyata jembatannya terendam. Setelah berputar cukup jauh, mencari jembatan yang lebih tinggi, masih juga harus menggulung celana ke atas, agar bisa melewatinya dan melintasi jalan-jalan di perumahan Kelapa Gading yang juga masih terendam air. Di mana-mana air, lalu semua ini salah siapa? Tuhan tidak bisa disalahkan, pun bukan karena kemurkaan Tuhan. Ini salahku dan salah semua sesamaku manusia, tapi ini tetap duniaku.
Alamat yang diberikan tidak begitu jelas. Nomer telepon yang bisa dihubungipun tidak nyambung-nyambung. Mulai putus asa, hari sudah sore, perut lapar, tas terasa semakin berat, tapi tujuan juga belum ketemu. Inginnya kembali ke menara gading (Kolese Kanisius). Kalau begitu, masakan, Yesus harus kembali ke surga (kontemplasi penjelmaan). Tidak, pokoknya jalan terus, percuma sudah perigrinasi.
Sekitar jam 5 sore, temanku kembali dari pencarian (secara bergantian -- untuk menghemat tenaga), akhirnya tempat tujuan ketemu. Proyek bangunan yang dimaksud, untuk sementara waktu ditinggal oleh tukang-tukangnya, karena banjir. Kami disambut oleh seorang bapak, yang ditugaskan sebagai penjaga kantor dan gudang proyek. Dia mempercayai kami, ketika kami menunjukkan nomer telepon Pimpro dengan benar. Dia adalah orang pertama yang menerima dan mempersilahkan kami istirahat di bedeng. Bahkan, malam itu juga, dia banyak cerita tentang dirinya, terlebih kelemahannya kalau menghadapi cewek (padahal itu privasinya). Bagaikan sang gembala yang memberikan tumpangan dan memberikan kehangatan bersama ternaknya di kandang Betlehem.
Beberapa anak masuk pula ke bedeng. Pakaiannya tidak karuan. Ada yang rambutnya gondrong dan berwarna merah (pirang). Nah, pasti ini anak-anak proyek! Sepintas perawakan mereka menakutkan, namun setelah berkenalan, ketahuanlah bahwa lingkungan kerja yang membuat mereka menjadi demikian.
Kedatangan kami sebenarnya kelihatan aneh. Kami dianggap orang KKN, ada juga yang menganggap teknisi lapangan kiriman pak Budi (Semarang). Melihat tas-tas besar yang kami bawa dan tampang bersih, mereka tak mudah percaya bahwa kami sungguh-sungguh mencari pekerjaan. Tanpa wasiat dari pak Budi, melamar pekerjaan di proyek ini pasti susah, karena beberapa bulan sebelumnya terjadi kasus pencurian yang melibatkan tukang-tukang yang baru saja kerja beberapa hari di tempat ini.
Aku ditempatkan menjadi kuli, membantu tukang batu. Aku mencoba mengingat-ingat pengalaman membangun kapel La Storta. Kalau tidak bisa, aku melihat cara kerja anak-anak proyek. Teman-teman kerjaku sangat beragam: tukang batu—keramik--kayu (mayoritas) berasal dari Purwodadi, tukang cat dari Cilacap, tukang listrik (dan pipa) dari Tegal, dan tukang lapangan Tenis dari Tulungagung. Masih ada beberapa yang lain (yang ditinjau dari tempat asalnya), yang dalam kategori minoritas: dari Lampung, Banten, dan Sunda.
Pada umumnya, latar belakang mereka adalah masyarakat desa. Selepas lulus SD, mereka memberanikan diri untuk merantau. Tampaknya bagi mereka, merantau adalah sesuatu yang menarik, menantang dan memberikan masa depan, ketimbang menjadi petani.
Umumnya, bekerja di proyek, terlebih dahulu harus menjadi kuli. Sehingga tidak mengherankan bahwa teman-teman kuliku adalah anak-anak yang baru lulus SD. Di antara kuli-kuli aku termasuk di-tua-kan: badanku besar, lulusan SMU, dan umurnya sudah tua. Aku cukup akrab dengan mereka. Ketika kami pindah, dari bedeng ke sebuah kamar kosong di proyek Mess itu, hampir setiap akan dan sesudah kerja, ada saja yang masuk dan mengajak ngobrol -- selalu ramai.
Berbeda dengan para tukang, interaksi mudah terjadi saat bekerja. Ada tukang yang enak diajak bicara, tapi ada juga yang ingin terus menunjukkan kesuperioritasannya. Bahkan aku pernah melihat seorang tukang hampir berkelahi dengan kulinya.
Sebenarnya, hubungan orang per orang, entah antara kuli dengan tukang, atau buruh dengan staf proyek (mandor) lebih melulu bisnis, kasarnya, demi kepentingan Gue. “Aku punya uang, kamu punya tenaga.” Di proyek, jarang ada yang namanya kekeluargaan (budaya yang ditawarkan pada kehidupan pertama mereka -- di desa). Wajar saja, kalau semuanyapun serba seadanya. Jaminan kesehatan hanya sebotol betadine. Kalau tidak dilihat staf proyek, kerjanya asal-asalan (Asal Bapak Senang), tanggungjawab kurang. Kalaupun ada yang berlaku sebaliknya, mungkin hanya segelintir orang. Yang jelas cara bertindak seperti itu populer di mana-mana, entah di proyek ini atau di proyek lain. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Selalu saja mereka mengeluhkan soal bayaran. Tapi, sebenarnya bukan itu.
Inilah kenyataannya. Dunia memang keras. Dunia telah menciptakan lingkungan keras bagi mereka. Bahkan itu mengkondisikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang single fighter. Solidaritas yang ada hanya semu, sebatas teman judi (main kartu dan toto gelap) atau mabuk, bahkan teman ke pelacuran.
Tidak jauh berbeda dengan masyarakat di sekitar proyek. Di sana ada 2 komunitas besar. Perumahan Kelapa Gading terkenal dengan perumahan elite (menengah ke atas). Ini memang diperuntukkan bagi warga TNI-AL. Begitu besarnya perhatian pemerintah kepada pengaman negara. Sekecil-kecilnya pangkat mereka, kehidupannya tetap terjamin. Hanya saja, cara kerja mereka tergantung dari peluit, yang kadang-kadang melampaui suara hati. Di batas perumahan ini, terhampar rumah-rumah kecil yang memanfaatkan lahan di pinggiran Kali Sunter. Kontras sekali, sebab yang satu ini kehidupannya menengah ke bawah.Dari ketiga komunitas yang kujumpai ini, sebenarnya, inti persoalannya sama: Bagaimana bisa hidup merdeka sebagai manusia dan survive di dalamnya? Hanya saja bentuk dan cara yang dilakukan beraneka ragam. Ada yang menindas, ada yang manutan (ABS). Ada yang kerja keras, ada yang duduk santai. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan seterusnya.


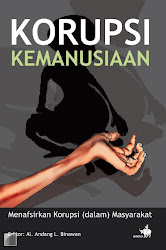








Tidak ada komentar:
Posting Komentar