
Hujan tidak juga kunjung reda. Hawa dingin semakin menyengat. Dengan berbekal cahaya temaram lampu taman, aku mencoba berjalan menyisir gang, dengan tujuan sebuah kamar di bilangan bangunan tua. Kamar nomor 21, tujuanku. Kira-kira, delapan meter di muka kamar itu, aku disambut dengan sebuah ukiran kayu besar yang menempel pada dinding di sebelah kiri. Dari ukiran itu terbaca, “Dengan langkah berat, aku sampai di Emmaus. Mataku terhalang seperti dahulu pada murid-murid-Nya. Namun, hatiku berkobar karena Dia di Emmaus.” Samar-samar, aku masih bisa membacanya, dan ukiran itu memperingatkanku bahwa aku telah memasuki bangunan yang begitu luas dan besar ini. Inilah wisma Emmaus, di mana romo-romo yang sudah sepuh tinggal dan bekerja sebagai pendoa sambil menantikan hari terakhir mereka.
Beberapa langkah di depan pintu Emmaus 21, di mana daun pintunya terbuka setengah, bau harum gaharu sudah menusuk hidungku. Jam 2 pagi ini, aku dibangunkan oleh temanku, bahwa ada berita berkabung, “Romo Topo meninggal!” Sungguh, suasana sedingin ini membuat kulitku merinding untuk memasuki kamar itu.
Sejurus tanganku membuka daun pintu itu, aku terkejut karena bed yang biasanya berada di sisi lain dari kamar berbentuk L ini, kini sudah berpindah ke tengah kamar, persis satu setengah meter di dekat pintu. Di atas bed itu, tampak seorang terbaring tak bergerak dan dari kaki hingga bahunya telah diselimuti kain putih. Bed itu terlalu besar untuk ukuran orang yang terbaring di atasnya. Di ujung bed, di dekat kaki, tertancap tiga batang gaharu di sebuah gelas yang berisi beras. Dari situlah bau harum tadi berasal. Di samping bed duduklah sendirian seorang laki-laki dengan sehelai kapas di tangannya.
Aku mendekati bed, dan perlahan-lahan ada bau aneh lain yang menyeruak masuk ke hidungku. Bau ini ikut tercampur dengan harumnya gaharu. Aku mencoba mencari dari mana asalnya. Di sebelah kiri pintu, ada sebuah lemari yang dipenuhi dengan perlengkapan pengobatan. Di bagian atas terdapat jarum suntik, botol infus, stetoskop, bejana aluminium, dan beberapa botol kecil yang berisi cairan suntikan. Di bagian bawah terdapat kain-kain putih dan beberapa pakaian. Tapi, bukan itu sumber bau aneh itu, karena bau obat tentu saja khas dan berbeda dengan bau aneh yang tercium olehku.
Arah pandanganku bergeser ke kanan dan mencoba menyisir ruangan itu. Pandanganku tertabrak pada sebuah TV 21 inchi merk Sony dan seperangkat telepon. Kemudian aku mencoba memalingkan ke sisi lain dari ruangan, di mana, sehari yang lalu, bed yang sekarang di tengah kamar, berada di situ. Bagian ini khusus untuk perawatan bagi romo-romo sepuh yang berada dalam kondisi kritis. Memang demikianlah Emmaus 21 digunakan, selain untuk kamar bersemayam bagi yang sudah meninggal, sehari-harinya digunakan juga untuk perawatan khusus.
Di tempat tadi ada sebaskom peralatan kedokteran yang tampaknya pernah dipakai. Ada botol infus bekas dan kain basah. “Bukan itu,” pikirku. Kembali aku menggeser kepalaku dan menatap sebuah ruangan di sebelah kanan pintu masuk. Ada WC. Pintunya tidak tertutup rapat, sehingga dari sudut kecil penglihatan dan celah-celah sempit penciuman, aku dapat menangkap bahwa WC itu bersih dan tidak ada bau aneh keluar dari WC itu.
Aku heran. Ruangan berukuran 12 meter persegi ini tidak menyisakan barang lain yang bisa kuamati sejenak untuk mencari sumber bau aneh tadi. Lalu, aku mengalihkan perhatian pada tubuh yang terbaring ini. Yang terlihat dengan jelas dari bagian tubuh ini hanyalah bagian kepalanya. Lubang hidung dan telinga telah ditutupi dengan kapas. Dan setiap beberapa saat, laki-laki penunggu tadi mengusapkan kapas di bagian pinggir mulutnya. Ada cairan yang keluar dari mulutnya. Aku mencoba memperhatikan lebih teliti.
***
Persis 5 bulan yang lalu aku mengambil kesempatan mengisi liburan ekskursi di Padepokan Bumiku. Setelah sekian lama mengharap, baru kali ini aku bisa ke padepokan yang begitu sederhana ini. Di salah satu sudut halaman aku sempat membaca ukiran kayu bertuliskan “memetri bumi anjejagi gesang”. Sedangkan di sudut lain tertera, “Alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tak bisa hidup tanpa alam.” Aku tertegun dengan untaian kalimat itu, dan seiring dengan ketertegunan itu, aku pun tak pernah habis pikir dengan perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan romo Topo demi lestarinya lingkungan hidup.
Baru sejam di padepokan, aku sudah diajak berkeliling kebun dan ladang. Semua kebutuhan dan perlengkapan hidup di padepokan itu tercukupi lewat pengolahan alam yang arif. Untuk konsumsi harian, ada sayuran dan buah-buahan kebun. Untuk tambahan protein, ada peternakan ayam dan sapi. Di beberapa sudut tempat disediakan dua jenis kotak sampah, yang satu berlabelkan sampah organik, yang lain non-organik. Untuk kebutuhan memasak harian tidak perlu minyak, rupanya ada digester biogas. Bahkan untuk penerangan malam hari, tempat ini mengandalkan pembangkit tenaga air dari aliran sungai di ujung ladang.
Wah, aku sungguh terkesan dengan kehidupan semacam ini, bahkan tidak jarang anak-anak sekolah datang untuk belajar mengenal alam di padepokan ini. “Kalau kita dapat melayani alam, maka alam juga akan memberikan sesuatu,” katanya suatu kali. Aku setuju. Alam benar-benar sudah lelah menghadapi tingkah manusia, terlalu banyak berkorban, tetapi jarang sekali dihargai.
Di hari berikutnya aku diajak romo untuk membantu menyiangi rerumputan di kebun kacang. Ketika hari semakin terik, romo masih tetap setia melanjutkan pekerjaannya. Aku sempat mengeluh karena panas. “Kamu tuh gimana tho, wong yang membuat bumi ini semakin panas khan kamu sendiri, koq sekarang gak mau menanggung perbuatanmu sendiri.” Aku terhentak. Dan semenjak itulah aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak merusak lingkungan.
***
Aku baru sadar kalau bau itu berasal dari cairan di mulutnya. Romo Topo meninggal karena sakit Lever kronis. Air yang keluar dari mulutnya berasal dari pembuluh-pembuluh darahnya yang pecah. Hampir seluruh hidupnya dibaktikan dalam totalitas memperjuangkan kelestarian alam. Sampai-sampai dia seringkali lupa diri bahkan dengan kesehatannya sendiri.
Aku mulai menundukkan kepala dan berdoa. Dalam hening, aku mengharu, betapa dia begitu dekat dengan alam, sehingga karena kedekatan itulah dia semakin dekat pula dengan Sang Pemilik alam itu.
Beberapa menit kemudian, aku tinggalkan kamar itu. Udara di luar semakin dingin. Hujan juga masih cukup deras. Dan waktu terus bergeser mendekati fajar. Aku melangkah kembali ke kamarku. Selamat jalan, Romo!***
Yogyakarta, Agustus 2008


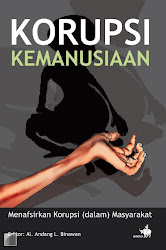








Tidak ada komentar:
Posting Komentar